Ia duduk di kursi kecil sambil memandangi hujan bulan Desember. Di selasar kamar itu udara dingin meresap di kulitnya. Pori-pori kulitnya bergetar. Sore itu ia sendirian. Tapi kertak hujan yang menimpa atap terdengar bergantian. Tak banyak yang bisa ia lihat dari sudut tempatnya duduk saat itu. Hanya genting-genting rumah yang dimakan usia, dinding rumah bagian belakang yang dibiarkan tak terplester, berlatar sepotong gunung yang bertudung awan gelap.
Ia pandangi kembali air hujan yang jatuh. Dengarkan kembali ricik hujan. Tiba-tiba ia tersadar. Seolah ia baru mengalami saat seperti ini. Butir air yang seperti mutiara itu, irama hujan yang menyegarkan itu. Derau hujan yang sengau itu. Getar itu. Hal-hal yang sederhana namun selalu tersisih. Hal-hal yang tak selalu mendapat tempat dalam kehidupan...
Ia tersadar : Ia tak punya waktu untuk hal yang remeh temeh lagi.
Sudah tak ingat kapan ia terakhir kali menyengaja memandang hujan seperti ini. Sejak ia selalu tergesa. Sejak ia sibuk dengan hal-hal besar namun mematikan hal-hal kecil yang sederhana dalam dirinya...
Ingin ia berdiri lalu pergi ke luar memesan secangkir kopi panas di warung ujung jalan, tapi tampaknya hujan akan turun sampai ujung malam nanti.
Merayakan ide, makna, rasa dalam bahasa. Sebelum terperangkap dalam ketidaktahuan dan ketidakmampuan mengungkap.
19 December 2008
03 December 2008
Jumpha Lahiri
Di tengah himpitan segala kewajiban menyelesaikan skripsi : ngitung tren produksi ikan tuna; buat grafik-grafik, buat peta fishing ground kapal longline, menekuni laporan-laporan dan artikel-artikel, bolak-balik ke kampus, maka baca baca buku ringan macam cerita pendek sungguh dapat menjadi pelipur frustasi.
Buku kumpulan cerita pendek yang selama dua minggu ini tak jauh dari jangkauan saya adalah bukunya Jumpha Lahiri yang berjudul Penafsir Kepedihan.
Sang penulis, Jumpha Lahiri, lahir dari orang tua keturunan Bengali, India, namun ia lahir di London dan besar di Amerika sekaligus kemudian menjadi warga negara Amerika. Koleksi cerita pendeknya, Interpreter of Maladies (Penafsir kepedihan), memenangi Pulitzer kategori fiksi pada tahun 2000, setelah sebelumnya meraih penghargaan The Hemingway dan Newyorker untuk kategori buku pertama terbaik.
Seingat saya, dulu, pertama kali saya mengenal nama Jumpha Lahiri bukanlah lewat karya tulisnya. Saya mengenalnya lewat sebuah film yang berjudul The Nameshake. Sebuah film yang diangkat dari novel pertama Jumpha Lahiri dengan judul yang sama.
Film the Nameshake sendiri berkisah tentang proses integralisasi satu keluarga kecil India ke kehidupan sesehari Amerika. Sebuah masalah yang mungkin akrab dengan hidup keseharian Lahiri waktu kecil. Gegar budaya orang tua. Krisis identitas para anak dihadapan eksotika akar keluarga. Pencarian dan penemuan jati diri menjadi warna keseluruhan film ini. Film yang bagus.

Seperti dalam film The Nameshake, dalam kumpulan cerpennya pun Jumpha Lahiri masih bertutur tentang masalah kehidupan etnis India yang tumbuh kembang di Amerika: Keterombang-ambingan, keterasingan, kerinduan, juga frustasi dengan hubungan tempat asal keluarganya menjadi perhatian penuh dalam tiap ceritanya. Konflik sesama migran, baur budaya, serta usaha mereka dalam menyelesaikan masalah mewarnai cerita-cerita pendeknya.
Kesederhanaannya bercerita, penuh perhatian pada detil dan hal kecil dalam kehidupan, sosok karakter yang ditampilkan... semuanya sungguh memikat. Belum lagi tabur deskripsi aksesoris dan furnitur yang tersebar di seluruh cerita. Sungguh menyenangkan untuk dibaca.
Akhirnya, saya merasa beruntung masih dapat baca buku tersebut di tengah tumpukan kesibukkan (lebih tepatnya tekanan). Bisa melihat dengan lebih dekat kehidupan para etnis India di tanah Amerika.
Buku, memang seperti kata Jumpha Lahiri yang tertutur lewat karakter kakek Gogol Gangguli, sang protagonis, dalam The Nameshake,
"That is what books are for. To travel the world without moving an inch."
Semangat untuk terus membaca buku di sepanjang akhir tahun ini.
gambar buku untuk interpreter of maladies saya cari di google tapi gak ketemu-ketemu yak?
Buku kumpulan cerita pendek yang selama dua minggu ini tak jauh dari jangkauan saya adalah bukunya Jumpha Lahiri yang berjudul Penafsir Kepedihan.
Sang penulis, Jumpha Lahiri, lahir dari orang tua keturunan Bengali, India, namun ia lahir di London dan besar di Amerika sekaligus kemudian menjadi warga negara Amerika. Koleksi cerita pendeknya, Interpreter of Maladies (Penafsir kepedihan), memenangi Pulitzer kategori fiksi pada tahun 2000, setelah sebelumnya meraih penghargaan The Hemingway dan Newyorker untuk kategori buku pertama terbaik.
Seingat saya, dulu, pertama kali saya mengenal nama Jumpha Lahiri bukanlah lewat karya tulisnya. Saya mengenalnya lewat sebuah film yang berjudul The Nameshake. Sebuah film yang diangkat dari novel pertama Jumpha Lahiri dengan judul yang sama.
Film the Nameshake sendiri berkisah tentang proses integralisasi satu keluarga kecil India ke kehidupan sesehari Amerika. Sebuah masalah yang mungkin akrab dengan hidup keseharian Lahiri waktu kecil. Gegar budaya orang tua. Krisis identitas para anak dihadapan eksotika akar keluarga. Pencarian dan penemuan jati diri menjadi warna keseluruhan film ini. Film yang bagus.

Seperti dalam film The Nameshake, dalam kumpulan cerpennya pun Jumpha Lahiri masih bertutur tentang masalah kehidupan etnis India yang tumbuh kembang di Amerika: Keterombang-ambingan, keterasingan, kerinduan, juga frustasi dengan hubungan tempat asal keluarganya menjadi perhatian penuh dalam tiap ceritanya. Konflik sesama migran, baur budaya, serta usaha mereka dalam menyelesaikan masalah mewarnai cerita-cerita pendeknya.
Kesederhanaannya bercerita, penuh perhatian pada detil dan hal kecil dalam kehidupan, sosok karakter yang ditampilkan... semuanya sungguh memikat. Belum lagi tabur deskripsi aksesoris dan furnitur yang tersebar di seluruh cerita. Sungguh menyenangkan untuk dibaca.
Akhirnya, saya merasa beruntung masih dapat baca buku tersebut di tengah tumpukan kesibukkan (lebih tepatnya tekanan). Bisa melihat dengan lebih dekat kehidupan para etnis India di tanah Amerika.
Buku, memang seperti kata Jumpha Lahiri yang tertutur lewat karakter kakek Gogol Gangguli, sang protagonis, dalam The Nameshake,
"That is what books are for. To travel the world without moving an inch."
Semangat untuk terus membaca buku di sepanjang akhir tahun ini.
gambar buku untuk interpreter of maladies saya cari di google tapi gak ketemu-ketemu yak?
26 November 2008
Langit

Langit, bauran awan bergugus, warna tersapu tanpa mengganggu. Di awal hari atau di ujung senja. Merah aprikot, indigo, putih, biru yang sebiru-birunya, atau yang manapun. Sekedar menatapnya, sekejap atau lekat, dan padanya serahkan lelah yang memeluk diri.
Langit, di mana pandang tak terhalang. Tak ada tiang, tak ada atap dan sekat. Tak berbatas. Umum yang luas namun tetap privat. Bulan, mentari, bintang, berganti menghias. Harapan masa depan, rahasia yang tak tersingkap. Saksi segala catatan peradaban.
Langit, gantungan harapan dan cita-cita. Carik kenyataan diam-diam berhenti menyelimuti. Sekedar merindu mimpi selanjutnya. Mendung datang menghalang pandang. Bisik tugas dalam benak menyeruak memeluk. Aku melangkah pergi.
Malang, November 2008.
Saat langit biru yang sebiru-birunya menjadi langka.
25 November 2008
Fitnah
kebenarannya dipenggal dari cerita
Kejujurannya dirampas pada kata.
Stigma menghapus fakta
seribu dusta menyatu pada tiap aksara.
hanya bala yang terpasang pada kata
yang menjadi seribu gada
yang menghantam raga.
hanya bencana yang datang bersama cerita
untuk menoreh seribu luka
pada dasar jiwa.
kau, kata sarat dusta,
cerita penuh bisa,
yang menyapaku di tikungan jalan.
Tapi, tak sudi aku menjawab
apa yang berawal dari hati pemakan bangkai.
Malang, November 2008
Kejujurannya dirampas pada kata.
Stigma menghapus fakta
seribu dusta menyatu pada tiap aksara.
hanya bala yang terpasang pada kata
yang menjadi seribu gada
yang menghantam raga.
hanya bencana yang datang bersama cerita
untuk menoreh seribu luka
pada dasar jiwa.
kau, kata sarat dusta,
cerita penuh bisa,
yang menyapaku di tikungan jalan.
Tapi, tak sudi aku menjawab
apa yang berawal dari hati pemakan bangkai.
Malang, November 2008
22 November 2008
bahasa Suroboyoan...

bagaimana bahasa Suroboyoan dalam prespektif budaya Jawa?
Beberapa hari yang lalu, saya diberi dua buah film indie pendek oleh seorang teman. Satu berjudul ‘Grammar Suroboyo’ dan satu lagi berjudul ‘Bahasa Suroboyoan’. Kedua film tersebut di produksi oleh Si Ikin, nama dari sebuah komunitas anak muda Surabaya (begitu katanya). Film yang berdurasi tidak lebih dari delapan menit tersebut bercerita tentang percakapan antara dua orang yaitu Suro (ikan hiu) dan Boyo (buaya). Dalam percakapan tersebutlah disisipkan bahasa Suroboyoan. Sebuah bahasa yang kontennya (jika di daerah lain, Malang misalnya) adalah kata-kata yang diperuntukan untuk (maaf) mis*h, marah-marah dan serapah.
Dari judul film tersebut, mungkin dalam hati Anda akan bertanya : “Apakah benar orang Surabaya semua memakai ‘grammar Suroboyoan’ yang diperlihatkan dalam dialog film si Ikin tersebut?” Saya tidak tahu. Mungkin mereka benar orang Surabaya dan benar-benar menggunakan ‘grammar Suroboyoan’. Tapi Andapun tahu, banyak orang Suroboyo tidak menggunakan ‘grammar Suroboyoan’.
Tapi masalahnya tidak sampai disitu. Walaupun tidak semua orang Suroboyo menggunakan grammar Suroboyoan, adanya film tersebut jelas menunjukkan adanya eksistensi dari pengguna bahasa Suroboyoan tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan ‘bahasa Suroboyoan’ dengan budaya induknya atau bahasa Jawa? Apakah pengguna ‘bahasa Suraboyoan’ dalam hal ini bisa disebut Jawa? Lalu dalam konteks apa seseorang itu di sebut Jawa?
Bagi masyarakt pasca-pertanian, masyarakat yang masih menganggap hirarki sosial sebagai pranata sosial, kerukunan dan keharmonian adalah sesuatu yang sangat penting. Maka, bahasa yang berkembang dan dikembangkan adalah bahasa antara lain untuk menjaga sistem nilai serta memperkukuh nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu bahasa yang dianggap cenderung merusakkan kerukunan dan harmoni akan dihindari dan dicegah.
Sayangnya nilai kerukunan dan harmoni yang begitu sentral dalam sistem budaya tersebut ternyata telah menciptakan berbagai sikap yang khas dalam masyarakat. Ia –secara tidak langsung maupun lansung telah menciptakan “budaya malu”, “budaya rikuh”, “segan” atau mungkin juga budaya “enggan”- Ia mendorong tumbuhnya keengganan untuk berkonfrontasi langsung atau memulai suatu konflik. Ia menganjurkan lebih baik menghindari pertengkaran daripada menyambutnya. Ia akan menekankan pada sikap peka terhadap kemungkinan munculnya rasa tersinggung pada orang lain.
Maka (yang saya tahu), orang Jawa sudah dianggap ‘jowo’ apabila telah memiliki kepekaan dalam konteks tersebut. Ukuran ‘halus’, ‘beradab’ dan ‘tahu adat’ sangat ditentukan oleh kepekaan penguasaan jurus kepekaan tersebut. Maka bahasa yang hadir adalah sebuah bahasa pergaulan yang penuh ungkapan pelembut. Walaupun dengan tujuan mengkritik, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang semu, bahasa sindir, dan bahasa yang berbunga-bunga. Dan dalam konbteks ini bahasa Suroboyoan tidak mendapat tempat karena sifatnya yang terus terang dan apa adanya serta (diselingi) ‘misuhan’.
Lalu, dari itu semua, di mana ‘Bahasa Suroboyoan’ ini ditempatkan? Masih bisakah disamakan dengan bahasa Jawa? Atau justru ‘grammar Suroboyoan’ adalah antitesis dari bahasa Jawa?
Entahlah...
Yang jelas saya tidak berani untuk menggunakan bahasa-bahasa yang ada dalam film pendek tersebut atau ‘grammar Suroboyoan’. Apalagi ketika hidup dalam lingkungan budaya di mana gestur terkecil pun punya muatan tata krama.
Lalu apa yang diinginkan oleh anak-anak Suroboyoan tersebut? Apa yang bisa dilihat dan dapat diambil dari film buatan si ikin tersebut?
Lagi-lagi entahlah...
Bahasa emang punya aturan gramatik, ‘mood’ dan ‘feeling’ nya sendiri-sendiri sehingga menggunakan bahasa yang ‘bebas’ dalam sebuah masyarakat tidak selalu bisa dibenarkan. Atau justru barangkali ini adalah langkah awal dalam mencari dan merumuskan bahasa baru yang tidak terlalu bergantung pada konteks nilai keselarasan hirarkis. Suatu bahasa yang cukup sopan, elegan, tanpa harus merunduk-runduk kebawah dan sering mendongak ke atas.
Ah...Entahlah?
Tapi barangkali, mungkin konteks orientasi budayanya yang bisa dipetik dari film tersebut. Bahwa ia menawarkan hidup dalam sebuah masyarakat egaliter dan sistem yang sangat terbuka. Masyarakat yang sama hak dan sama derajat yang dilihat dengan penggunaan bahasanya dalam percakapannya.
Ah.....Entahlah... Kang Mas, Mbakyu...
Ini semua hanya memaksa saya untuk terus belajar lagi hidup di sebuah budaya dengan tradisi, cara hidup, yang padat dengan tata krama dan petatah-petitih ini.
20 November 2008
August Rush
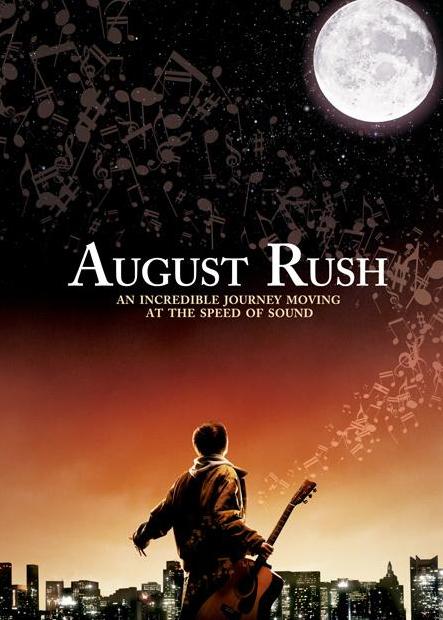
Dihadapan para jenius kita selalu terkagum-kagum. Terheran-heran. Takjub bagaimana alam bekerja terhadap para jenius. Desir angin, rintik hujan, riuh jalan raya, hening alam raya, ternyata mampu menjadi sumber inspirasi dalam pekerjaan sang jenius. Bagaimana riuh-ramai jalan raya dapat di-orkestra-i menjadi sebuah alunan musik yang mengagumkan. Hebat? Sangat.
Itulah kesan yang kuat yang saya dapat saat saya nonton film August Rush. Film yang mengisahkan perjalanan seorang anak, Evan Taylor, dalam mencari kedua orang tuannya lewat alunan musik.
Kuat dan mengharukan… sang pemeran utama mampu menampilkan akting yang menawan. Bagaimana perasaan penonton –saya- diaduk-aduk tak karuan selama film berjalan. Di buat menahan nafas- berlama-lama. kita serasa terus akan selalu bertanya bagaimana kisah ini akan berakhir...
Sayang, ending film ini kurang sedikiiiitttt lagi. Sutradara sepertinya menahan untuk tidak menampilkan kegembiraan yang meluap-luap di akhir cerita.
Dari semua itu bagus. I’m like it.
15 November 2008
Segenggam Cinta dari Anis Matta

Perasaan apa yang melanda para pecinta ketika cinta menyapa? Dari mana cinta datang dan kemana cinta menghilang? Apa cinta itu? Sepertinya pertanyaan seputar cinta tak akan pernah habis dan selesai. Manusia memang bisa bertanya, tapi sepertinya manusia tak akan pernah menemukan definisi yang paling pas, yang paling tepat dan paling seksama. Pasti selalu ada yang lemah, dan tidak setara, dalam setiap definisinya tentang cinta. Ada yang tak sepenuhnya bisa ia ungkapkan ketika berbicara cinta. Sebab itu mungkin manusia membuat media-media abstrak: puisi, alegori, lagu, lukisan, mitos, untuk menggambarkan cinta, untuk menggambarkan seluruh fenomena emosi dan stimultan yang tengah mereka rasakan, namun tak sepenuhnya juga bisa diungkapkan.
Mungkin dari keterbatasan pemahaman manusia tentang cinta itulah sebuah tulisan pendek hadir tiap dwi mingguan selama tiga tahun, di sebuah majalah. Hanya satu halaman namun begitu dinanti-nanti oleh para pembaca setia majalah tersebut. Kolom, yang diasuh oleh stamina satu orang tersebut hadir dengan sebuah gayanya yang khas.
Lalu apa sebenarnya yang diinginkan Anis Matta, sang penulis, seorang da’i, seorang politikus terkemuka, dengan tulisan-tulisannya tersebut?
Satu hal yang jelas, Anis hadir kepada sidang pembaca dengan menawarkan sebuah jalan alternatif. Sebuah wacana, sebuah ide, sebuah gagasan baru tentang topik perbincangan yang tak selesai-selesai selama berabad-abad itu. Mungkin tidak semuanya baru tapi Anis mampu mengemas dan menampilkannya menjadi sesuatu yang segar dan pembaca ‘dipaksa’ untuk merenungkannya. Sehingga setiap tulisan dalam Serial Cinta adalah sebuah cerminan pendekatan terhadap ide besar. Kesederhanaannya bercerita, limpah perhatiannya pada detil dan hal kecil dari kehidupan tentang pengelolaan cinta tersebar ditiap tulisannya, spontan dan konsisten memberikan kearifan dalam memandang fenomena cinta, menjadi gagasan tiap-tiap tulisannya.
Maka tulisannya mencerminkan sebuah kekuatan dalam kelembutan –sebuah gaya yang jarang ditemukan dalam penulisan sebuah kolom di majalah-majalah lain. Tabur metafora yang menghiasi tiap tulisan, kata putik yang lincah namun tetap terkendali, kombinasi antara kata kutipan dan kisah yang serasi, semua meluncur dari jemarinya. Semuanya dapat menunjukkan bagaimana Anis serius dan intens dalam memberi daya gugah dalam tiap tulisannya sekaligus menunjukkan kehadirannya ketika berhadapan dan ‘mengobrol’ dengan para pembacanya.
Lalu dari mana Anis mendapatkan daya gugah sebesar itu? Semua itu memang bisa dilihat sebagai kelihaian menulis dan keahlian menyampaikan gagasan. Tapi tampaknya bukan hanya itu yang menjadi kekuatan dalam tiap tulisannya. Jika konsepsi adalah sebuah pondasi di mana sebuah tulisan akan dibangun, maka dapat dipandang konsepsi Anis adalah konsepsi yang sudah matang dan selesai.
Oleh karena itu di dalam 73 tulisannya, kita tidak bisa mendeteksi Anis bicara tentang, atau merekam, kejadian dalam kehidupan pribadinya. Ia tidak menjadi topik utama atau menjadi lakon utama dalam tulisannya. Anis tampak telah lepas dari masalah-masalah pribadinya. Ia sudah tidak terjebak dalam pertanyaan kegelisahan atau pencarian-pencarian dalam misteri, yang justru biasanya terjadi ketika seseorang menulis tema cinta, melainkan Anis datang ke dalam kehidupan dengan tulisannya untuk memberikan penjelasan atau bahkan jawaban.
Setidaknya, ia menyampaikan apa yang bisa dan seharusnya ada ketika orang bicara dan mengelola cinta. Ia dengan kearifannya, seperti seorang guru, mengajari atau tidak, agar pikiran-pikirannya didengarkan dan direnungkan. Sehingga dalam membaca tiap tulisannya pembaca tidak dibawa larut keseluruhan dalam obrolan cinta yang tanpa ujung dan tak habis karena rasa terbawa romansa. Tapi di hadapan tulisan Anis akal kita disiapkan agar tetap terjaga walaupun rasa sedang berkelana.
Makanya dalam buku Serial Cinta, kita dapat melihat penuturan baru ketika berbicara cinta: sang penulis membedah fenomena cinta menjadi pecahan kecil-kecil, dianalisa, dideskripsikan lantas dikategorisasi yang semuanya menyebar dalam tiap tulisannya. Tapi dalam proses tersebut ia tidak terjebak dalam bahasa teknis dan narasi yang berbelit dan bercabang. Malah sebaliknya, Anis menuliskannya dengan apik dan penuh puitik. Melankolik tanpa jadi dramatik. Ia mampu memaparkan gagasan-gagasannya dengan cukup lengkap, menyentuh berbagai dimensi, serta sistematis dan tertib.
Tentu saja dalam penyampaian gagasannya Anis telah siap dengan catatan sejarah yang valid dan kutipan-kutipan serta kisah untuk menguatkan argumentasinya. Barangkali itu yang memang harus diyakinkan untuk mengguncang persepsi dominasi yang ada saat ini. Terutama untuk meyakinkah bahwa ‘suatu hal’ itu pernah terjadi di dunia di masa lalu dan ‘suatu hal’ tersebut masih mungkin untuk diulang hari ini.
***
Hal yang tampak kurang menarik dari Serial Cinta adalah penggunaan judul buku yang terasa kurang menggugah dilanjutkan dengan penjelasan judul yang terlalu mendramatisir. Sedangkan gambar sampul serta tata letaknya sepertinya tidak terlalu mendapatkan perhatikan yang serius dalam penggarapannya. Sehingga –bagi yang tidak pernah mengenal kolom Anis Matta- tampak terkesan isinya main-main terlebih bila disandingkan dengan judulnya yang terlalu mendramatisir.
Namun dari semua itu buku Serial Cinta tetap berharga untuk menjadi tambahan referensi bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang cinta dan ingin melihat cinta dalam warna yang berbeda. Anis memang telah menambah segenggam pasir pemahaman yang diambil dari bentangan gurun cinta. dan meskipun kita bertambah pengetahuan toh kita tetap sulit mendefinisikannya kembali tentang cinta.
Mungkin inilah yang dimaksud oleh penulis dalam cinta tanpa definisi-nya. bahwa cinta tak perlu definisi:
Cinta adalah kata tanpa benda, nama untuk beragam perasaan, muara bagi ribuan makna, wakil dari sebuah kekuatan tak terkira. (tapi) Ia jelas, sejelas matahari.
* Penikmat buku, Mahasiswa Universitas Brawijaya.
12 November 2008
Sarjana
Dunia akademis, menurutku, tak lebih dari satu permainan besar dengan peraturannya sendiri. Contohnya seperti pencapaian seorang mahasiswa dalam memperoleh gelar Sarjana di sebuah universitas, tak lebih dari mengikuti sebuah permainan dengan terus mematuhi semua peraturannya.
Dalam pencapaian gelar sarjana seorang mahasiswa harus diukur melalui satu set kriteria, salah satunya yaitu ikut andil dalam mempublikasikan karya ilmiah atau skripsi. Ada berbagai aspek dari karya ilmiah tersebut yang ditimang sebagai kriteria layak atau tidaknya menjadi bagian integral dunia akademik, antara lain adalah orisinalitas.
Dalam proses menghasilkan karya tersebut, seorang mahasiswa tak ubahnya seorang wiraswasta. Ia menghadapi ketidakpastian yang sama dengan seorang pebisnis. Ini saya berani bilang karena pengalaman dan pengamatan dalam melakukan penelitian di lapangan maupun di laboratorium
Seorang teman yang bekerja di lab mengeluhkan ternyata bekerja di lab tidak lebih mudah dengan bekerja di lapangan.Walaupun ada seribu satu hal yang mungkin bisa dikondisikan tapi ia juga menyimpan ironinya : bahwa ada seribu satu hal kemungkinan yang berjalan tidak sesuai dengan perkiraan. Apalagi mereka yang bekerja dengan ikan dan bakteri (khususnya bidang di natural science-lah). Saat eksekusi eksperimen, saat di mana data ditambang dan dihasilkan, adalah tahap paling mengerikan dari keseluruhan proyek. Data generating itu luamaaaaaaa pool.. dan mbosenin (begitu keluh teman saya) . Masalah sebar benih, rekam pertumbuhan, koleksi bakteri (yang ga mudah dan ga murah)... kerja berjam-jam berbulan-bulan hanya demi seruas data di tabel yang tak lebih dari dua halaman.
Sebenarnya tak jauh berbeda dengan mereka yang bekerja di lapangan, mondar-mandir sana-sini, ikut ngerusuhi dengan praktisi, wawancara ini itu, survey sana survey sini (menjadi pekerja sekaligus pelancong). walaupun tidak banyak hal yang bisa dikondisikan namun bagi pekerja lapangan ada satu kelonggaran dalam hasil laporan: margin kesalahannya tidak seketat mereka yang meneliti di lab.
Oleh sebab itu, tiap kali kita melihat satu hasil pekerjaan ilmiah yang berhasil sebenarnya kita tengah menatap satu senyawa antara ikhtiar untuk tidak berhenti dan serendipity, kebetulan yang manis. Oleh karena itu jika ada ada karya penelitian (ilmiah) yang berhasil dihasilkan seseorang, bisa dijadikan sebuah ukuran sebagai betapa uletnya orang tersebut bekerja (di sisi lain, betapa beruntungnya ia...) .
Tahap berikutnya yang ga kalah serius adalah menulis laporan dan artikel hasil penelitian. Dan inilah palang uji terakhir buat seorang calon sarjana. Mirip sebuah ritus seorang anak untuk diakui sebagai orang yang dewasa. Di sinilah seorang calon sarjana menyerahkan hasil laporannya untuk ditelaah, diperiksa oleh ‘orang dewasa’ di kultur akademik. Jika hasil jerih lelahnya dianggap cukup layak untuk mampir di ruang baca pekerja akademik lain, ia lulus, ia dilihat sebagai bagian integral dari dunia akademik. Jika tidak...
Mohon do’a nya.
Semoga berhasil dalam melewati palang uji terakhir.
Dalam pencapaian gelar sarjana seorang mahasiswa harus diukur melalui satu set kriteria, salah satunya yaitu ikut andil dalam mempublikasikan karya ilmiah atau skripsi. Ada berbagai aspek dari karya ilmiah tersebut yang ditimang sebagai kriteria layak atau tidaknya menjadi bagian integral dunia akademik, antara lain adalah orisinalitas.
Dalam proses menghasilkan karya tersebut, seorang mahasiswa tak ubahnya seorang wiraswasta. Ia menghadapi ketidakpastian yang sama dengan seorang pebisnis. Ini saya berani bilang karena pengalaman dan pengamatan dalam melakukan penelitian di lapangan maupun di laboratorium
Seorang teman yang bekerja di lab mengeluhkan ternyata bekerja di lab tidak lebih mudah dengan bekerja di lapangan.Walaupun ada seribu satu hal yang mungkin bisa dikondisikan tapi ia juga menyimpan ironinya : bahwa ada seribu satu hal kemungkinan yang berjalan tidak sesuai dengan perkiraan. Apalagi mereka yang bekerja dengan ikan dan bakteri (khususnya bidang di natural science-lah). Saat eksekusi eksperimen, saat di mana data ditambang dan dihasilkan, adalah tahap paling mengerikan dari keseluruhan proyek. Data generating itu luamaaaaaaa pool.. dan mbosenin (begitu keluh teman saya) . Masalah sebar benih, rekam pertumbuhan, koleksi bakteri (yang ga mudah dan ga murah)... kerja berjam-jam berbulan-bulan hanya demi seruas data di tabel yang tak lebih dari dua halaman.
Sebenarnya tak jauh berbeda dengan mereka yang bekerja di lapangan, mondar-mandir sana-sini, ikut ngerusuhi dengan praktisi, wawancara ini itu, survey sana survey sini (menjadi pekerja sekaligus pelancong). walaupun tidak banyak hal yang bisa dikondisikan namun bagi pekerja lapangan ada satu kelonggaran dalam hasil laporan: margin kesalahannya tidak seketat mereka yang meneliti di lab.
Oleh sebab itu, tiap kali kita melihat satu hasil pekerjaan ilmiah yang berhasil sebenarnya kita tengah menatap satu senyawa antara ikhtiar untuk tidak berhenti dan serendipity, kebetulan yang manis. Oleh karena itu jika ada ada karya penelitian (ilmiah) yang berhasil dihasilkan seseorang, bisa dijadikan sebuah ukuran sebagai betapa uletnya orang tersebut bekerja (di sisi lain, betapa beruntungnya ia...) .
Tahap berikutnya yang ga kalah serius adalah menulis laporan dan artikel hasil penelitian. Dan inilah palang uji terakhir buat seorang calon sarjana. Mirip sebuah ritus seorang anak untuk diakui sebagai orang yang dewasa. Di sinilah seorang calon sarjana menyerahkan hasil laporannya untuk ditelaah, diperiksa oleh ‘orang dewasa’ di kultur akademik. Jika hasil jerih lelahnya dianggap cukup layak untuk mampir di ruang baca pekerja akademik lain, ia lulus, ia dilihat sebagai bagian integral dari dunia akademik. Jika tidak...
Mohon do’a nya.
Semoga berhasil dalam melewati palang uji terakhir.
Cecak merayap
Cecak merayap di dinding ruang tamu berwarna biru
melihat nyamuk terbang kehilangan arah
sejenak berhenti merayap untuk mnegintai
di dinding ruang tamu berwarna biru.
Lumayan untuk makan malam pikir cecak.
nyamuk hinggap di dinding ruang tamu berwarna biru
rehat sejenak berhenti terbang
lupa sedang apa ia disini
di dinding ruang tamu berwarna biru itu
O, hendak cari makan teringat ia.
Sekejap ia merentangkan sayap hendak terbang
Sayang cecak sudah di hadapan.
Sukabumi 2007
melihat nyamuk terbang kehilangan arah
sejenak berhenti merayap untuk mnegintai
di dinding ruang tamu berwarna biru.
Lumayan untuk makan malam pikir cecak.
nyamuk hinggap di dinding ruang tamu berwarna biru
rehat sejenak berhenti terbang
lupa sedang apa ia disini
di dinding ruang tamu berwarna biru itu
O, hendak cari makan teringat ia.
Sekejap ia merentangkan sayap hendak terbang
Sayang cecak sudah di hadapan.
Sukabumi 2007
05 November 2008
kami putra-putri Indonesia...

Kita tak pernah tahu perasaan apa yang membadai dalam dada pemuda-pemudi itu. Apa yang berkecamuk dalam kepala mereka. Ketika pada akhirnya mereka harus mengucap ikrar. Bersumpah setia pada sebuah nama yang belum nyata. Sebuah nama yang hanya ada dalam benak mereka. Berjanji setia pada sebuah wacana, wacana yang juga belum selesai : Indonesia
Kita mungkin hanya dapat membayangkan mereka dari berbagai organisasi pemuda daerah, mungkin tak semuanya dikenal, berhimpun di sebuah gedung, yang tak terlalu besar, dengan penjagaan ketat tentara Belanda. Acara dibuka. Lalu beberapa pemuda maju ke mimbar bergantian memberikan orasi, selama dua hari sebelum diakhiri dengan sebuah permainan biola dari W.R. Supratman yang membawakan Lagu Indonesia raya...
Tapi kita mungkin tak pernah tahu persis, suasana apa yang melahirkannya. Ketika teks itu dirumuskan lalu disusun kata perkata. Kalimat per kalimat. Kekalahan yang dibalut harapankah? Sebuah optimismekah? Persiapan perlawanankah? Kita tak tahu persisis. Sama seperti kita tak pernah tahu apakah pemuda pemudi itu tak pernah bertanya apa Indonesia itu? Mana batasannya? Yang mana bahasa Indonesia itu?
Tak ada tanya ataukah memang tak ada jawab? Atau memang belum perlu ada jawab.
Sungguh kita tak tahu saat teks itu terumuskan. Bergetarkah tangan yang menuliskannya? Takzimkah mereka ketika berucap Indonesia? Bergemuruhkah dada mereka kita berucap 'Bangsa Indonesia'? Kita tak tahu. Hanya mereka yang diberi keistimewaan oleh sejarah untuk merasakannya.
Mungkin tak ada seorangpun yang bisa menjelaskan kepada kita apa, siapa yang menggerakkan roda nasionalisme -yang kata Soekarno disebut sebuah keinsyafan rakyat untuk satu bangsa - itu. Soegondo kah? Moh. Yamin kah? Ataukah sebenarnya justru mereka sendiri?
Kita hanya bisa melihat sebuah teks yang lurus. Ringkas. Tapi keras. Sekeras granit “...Bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia”.
Teks bersejarah itupun sampai kepada kita terlalu dini, bahkan sebelum duduk di bangku SMP. Pendek. Hanya tiga baris. Satu ideologi, satu kesatuan dan persatuan tentang Indonesia. Kita mengingatnya karena setiap tanggal 28 Oktober ada yang mencetak, ada yang membacakan kembali. Di upacara-upacara, Apel-apel.
Tapi sungguh kata-kata bisa direkam. Tulisan bisa dicetak kembali. Berulang-ulang. Berkali-kali. Tapi apakah emosi yang melatari dan menemani saat pemuda-pemudi itu mengucap sumpah bisa diulang kembali? Bisa dirasakan kembali oleh putra-putri Indonesia- kini. kalau tidak??
Lalu apakah itu berarti bahwa kita tidak akan mampu memahami kecintaan, kerinduan, harapan, dan kepemilikan akan sebuah nama seperti yang dirasakan pemuda-pemudi saat itu?
Tentu tidak. Semoga tidak.
Atau entahlah..
Biarkan itu diserahkan kembali kepada Putra-putri Indonesia. Mereka yang akan lebih tahu untuk menentukan arti separagraf Sumpah itu.
Sekarang saya hanya bisa mencoba membacanya kembali, dengan lirih sahaja : “Kami Putra putri Indonesia...”
:: Mungkin nanti malam saya akan berdo'a : Ya Allah ingatkan terus bahwa hamba ini juga adalah orang Indonesia ::
24 Okt-03 Nov 2008
04 November 2008
di kursi kamar
Aku terduduk di kursi kamar. Melamun tapi tak ada kopi panas. Buku-buku masih menumpuk tak tertata di sana sini. Capek. Lelah. Penat. Hari yang berat, tapi untuk saat ini. Tenggat sudah semakin dekat. Komitmen untuk menyelesaikan laporan skripsi bulan ini sepertinya mustahil terlaksana. Terhenti lagi. Mundur lagi. Satu, dua…tiga model statistika masih bermain di benakku. t-test, Anova..., SPSS...
“...Lha..itu kan untuk membuktikan variable bahwa kedua variable yang diperbandingkan berbeda secara signifikan... trus..kalau tak ada bukti aritmatik yang bisa ditampilkan... Lha kalau yang satunya itu.. Kalau parameter yang itu gak bisa di apa-apain lagi. Yah... ehmm...mungkin ga usah pakai t-test atau Anova, pakai SPSS saja kali ya biar cepet... atau mungkin..jelas pakai Anova, data untuk tiap daerahkan dianggap sama...aduh kalau gini pasti ujung-ujungnya ada uji BNT? Kalau ga salah yang seperti ini pernah baca deh? di laporannya siapa ya? Di mana yah... atau yang tadi di perpus ya.. Perasaan dulu nilai statistik sama Metil ga jelek-jelek amat deh.. ko sekarang nge-blank gini ya..”
Hidungku mulai terasa buntu. Flu yang semenjak musim hujan ini mengintip sudah tak malu menampakkan diri. Hari akan memulai malam. Hujan rintik mulai jatuh pelan. Kejap berikutnya hujan deras menutup pandang. Malang memang mulai hujan.
Sore hari sembari diiringi hujan selalu bikin suasana berbeda. Aroma tanah yang menguap, bau hujan yang tercium, seperti mengizinkan untuk bermelom-melow...
akhir Oktober 2008
“...Lha..itu kan untuk membuktikan variable bahwa kedua variable yang diperbandingkan berbeda secara signifikan... trus..kalau tak ada bukti aritmatik yang bisa ditampilkan... Lha kalau yang satunya itu.. Kalau parameter yang itu gak bisa di apa-apain lagi. Yah... ehmm...mungkin ga usah pakai t-test atau Anova, pakai SPSS saja kali ya biar cepet... atau mungkin..jelas pakai Anova, data untuk tiap daerahkan dianggap sama...aduh kalau gini pasti ujung-ujungnya ada uji BNT? Kalau ga salah yang seperti ini pernah baca deh? di laporannya siapa ya? Di mana yah... atau yang tadi di perpus ya.. Perasaan dulu nilai statistik sama Metil ga jelek-jelek amat deh.. ko sekarang nge-blank gini ya..”
Hidungku mulai terasa buntu. Flu yang semenjak musim hujan ini mengintip sudah tak malu menampakkan diri. Hari akan memulai malam. Hujan rintik mulai jatuh pelan. Kejap berikutnya hujan deras menutup pandang. Malang memang mulai hujan.
Sore hari sembari diiringi hujan selalu bikin suasana berbeda. Aroma tanah yang menguap, bau hujan yang tercium, seperti mengizinkan untuk bermelom-melow...
akhir Oktober 2008
11 October 2008
Buku Buatku
Membaca, buatku, adalah sebuah aktivitas mencari.. Tidak melulu tentang mencari jawaban tapi yang lebih penting dari itu : mencari pertanyaan (bukankah justru dengan bertanya jawaban tercari dan tertemukan?). Membaca berarti juga berpetualang: mata sekaligus sayap. Mata untuk melihat bentangan horison yang luas, dan sayap untuk membawa terbang menjelajahinya.
Oleh karena itu, buku adalah sebuah kapal bajak laut yang yang tak lelah mengarungi tujuh Samudera dan lautan terlarang. Yang perjalanannya lebih tua dari gugusan pulau di Samudera Atlantik. Mitos, hikayat, cerita perjalanan tertulis pada bendera yang berkibar di ujung tiang kapal. Lagu, bahasa, semangat, terukir pada dindingi-dinding kayu, terhirup bersama aroma garam yang menguap dari lautan.
Buku adalah setapak jalan menuju hutan tropis di pedalaman Afrika, yang penuh dengan perdu, sulur dan belukar, daun-daun yang lebar, dan lumut yang lembab. Di mana kota yang hilang, dengan kekayaan masa lalu, cerita-cerita tua di dinding gua, naskah-naskah kuno yang terpendam di ruang bawah tanah, menunggu tertemukan seseorang. Seperti Kota hilang di pedalaman Kongo yang dijaga gorila.
Buku juga berarti strategi perang, denting pedang, derap kuda, badai debu. Cinta sekaligus dendam, di perang besar Baratayudha. Di mana Abimanyu tertancap oleh puluhan senjata pasukan Kurawa sedang Resi Bhisma terhujam oleh seribu anak panah Arjuna.
Buku juga adalah teka-teki penuh misteri. Di mana Robert Langdon berjalan, berlari, dengan waktu di malam buta, mencoba memecahkan kode rahasia lukisan-lukisan Leonardo Da Vinci. Buku berarti juga penguak tabir misteri. Seperti Poirot yang menelengkan mata untuk memberi kesempatan sel-sel kelabu di kepalanya untuk bekerja dalam membuat gambaran besar dari kepingan-kepingan puzzle.
Buku adalah petunjuk jalan ke kotak harta yang terkubur berabad-abad. Kotak harta yang sarat petuah tentang kebijakan, kebajikan dan kebijaksanaan. Seperti Syaikh munir al-Gotbhan yang menulis sejarah kehidupan Rasulullah dari sudut yang berbeda sama sekali. Sebuah perjalanan kehidupan yang kaya hikmah, pelajaran, panduan, kejutan dan ketakjuban baru di tiap tikungnya.
Buku adalah sebuah gerbang, portal ke dunia yang sama sekali lain. Dunia di mana ada Peri Rumah yang sibuk menyiapkan makanan untuk pesta penyambutan murid baru di Hogwarts, dan ada Hobbit bertugas menghancurkan sebuah cincin ke kawah berapi.
Buku, menurutku, tak hanya mengabarkan fakta akan dunia luar: Migrasi ikan, hibernasi beruang. strategi burung manyar dalam menarik pasangan. Buku juga mengundang kita untuk menikmati benak dan emosi manusia. Menyaksikan konflik dan dilema kehidupan anak manusia. Buku mengajak kita untuk jadi kontemplatif, berdiam sebentar mengamati drama dan tragedi dalam hidup manusia lain, entah fakta atau fiksi, dan melaluinya bercermin mematut hidup sendiri.
Tapi hati-hati, karena ketenangannya, buku juga berpotensi untuk menenggelamkan, seperti telaga dan pasir hisap. Seperti mantra avada kadavera.
Itulah membaca dan buku buatku. Sebuah petualangan. Maka, buku yang tidak bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan, dan buku yang tidak bisa memberikan perjalanan dan pengalaman baru tiap kali membacanya, buku yang tidak bisa dibaca berulang-ulang, menurut ku bukan buku yang layak dibaca.
Buku pertama yang menjadi favoritku adalah Menikmati Demokrasi dan Dari Gerakan ke Negara. Berasal dari Kumpulan kolom di Majalah Saksi dan Majalah Hidayatullah. Walau tak dimaksudkan untuk menjadi sebuah buku, tapi dari isinya tergambar sebuah uraian satu tema besar. Di mana setiap kolom terasa begitu koheren dan terstruktur dengan yang lain. Sehingga antara satu kolom dengan yang lainnya saling menopang dan mengisi. Buku tersebut berlatar kondisi Indonesia kontemporer dengan solusi kearifan masa kenabian. Anis Matta, sang penulis, mampu menterjemahkan sebuah konsep gerakan dakwah yang besar dalam tulisan yang sederhana dengan gayanya yang khas: tak banyak kata, dengan diksi terpilih, semua diracik dengan bumbu prosaik lincah dan segar. Sesedap Mencari Pahlawan Indonesia dan Serial Cinta-nya yang juga jadi favoritku.
Buku ke dua yang juga menjadi pavoritku adalah : Kuartet Pulau Buru : Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Membaca ke empat buku tersebut serasa dimasukkan dalam benak sang tokoh tapi juga ke setting tempat dan waktu cerita berlangsung. Pram mampu memaparkan sejarah dari sudut kacamata lain. Di sanalah memang kekuatan Pram, mampu menggambarkan keadaan tempat, peristiwa sejarah, emosi jiwa, dan karakter tokoh yang begitu kuat. Sampai sekarang, ini kasus untuk saya, saya masih merasa sosok Minke, sang protagonis, tokoh sentral dari novel di atas, pendiri Syarikat Islam, benar-benar pernah hidup di awal Abad duapuluh.
Jika Pram begitu kuat dalam cerita-cerita sejarah Indonesia, maka Ahmad Tohari hebat dalam penuturannya tentang alam. Dengan penanya, burung alap-alap, jangkrik, kodok, bentangan sawah, mampu memberikan arti tersendiri tentang makna kehidupan. Dan dengan penuh puitik Tohari menyampaikannya. Makanya saya sangat senang dengan Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk nya. Sambil menikmati alam dan budaya Masyarakat Banyumas berlatar masa pemberontakan PKI, kita juga diajak mengikuti kisah lenggak-lenggok hidup Srintil dari sejak kecil dalam mencari sejatinya kehidupan.
Buku di atas tak lengkap tanpa mengikutkan buku lain : Burung-burung Manyar Romo Mangun, Max Havelaar nya Multatuli. Habis gelap terbitlah terang-nya kartini. Setelah Revolusi Tak ada Lagi dan Tuhan dan Hal-hal yang tak pernah Selesai serta Catatan Pinggir nya (khusus Caping tidak bisa saya nikmati lewat buku, susah carinya!) Goenawan Mohamad. Manhaj Haroki Syaikh Munir Al-Gothban. Serta yang terakhir kumpulan puisi Mata Pisau-nya Sapardi Djoko Damono.
Jumlah buku koleksi : layak lah untuk di sebut perpustakaan pribadi. Walau setelah diteliti lagi, ternyata tak seimbang memang jenis buku yang ada.
Buku yang terakhir dibaca: Sang Musafir Mohammad Sobary, Serial Cinta-nya Anis Matta, Aku, Buku dan Sepotong Sajak Cinta Muhidin M Dahlan, Horeeluya..! Arswendo Atmowiloto, Rahasia Membutuhkan Kata Harry Aveling, dan yang belum kelar-kelar Pergulatan Intelektual di Masa Kegelisahan sebuah buku untuk mengenang seratus hari wafatnya Romo Mangun.
book list yang ada tahun ini: Nyanyi Sunyi seorang Bisu-nya Pram, Olenka- Budi darma, Catatan Pinggir 7 Goen, Madilong, Tan Malaka (ini buku-buku yang susah dicari). Yang lainnya ada Laskar Pelangi Andrea Hirata,
Buku yang terakhir di beli :Sang Musafir sama serial Cinta.
Buku yang paling berkesan dan sering di baca: yah...judul-judul pertama yang di atas tadi.
Itu buku buatku yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Sekarang, kalau ada waktu terluang, sudilah kiranya Kang izul, Akh Andrik, Mbak Maul, untuk meneruskannya. Dan monggo kita simak apa sebenarnya buku buat mereka.
Maaff ya kalau merasa di teror.
Oleh karena itu, buku adalah sebuah kapal bajak laut yang yang tak lelah mengarungi tujuh Samudera dan lautan terlarang. Yang perjalanannya lebih tua dari gugusan pulau di Samudera Atlantik. Mitos, hikayat, cerita perjalanan tertulis pada bendera yang berkibar di ujung tiang kapal. Lagu, bahasa, semangat, terukir pada dindingi-dinding kayu, terhirup bersama aroma garam yang menguap dari lautan.
Buku adalah setapak jalan menuju hutan tropis di pedalaman Afrika, yang penuh dengan perdu, sulur dan belukar, daun-daun yang lebar, dan lumut yang lembab. Di mana kota yang hilang, dengan kekayaan masa lalu, cerita-cerita tua di dinding gua, naskah-naskah kuno yang terpendam di ruang bawah tanah, menunggu tertemukan seseorang. Seperti Kota hilang di pedalaman Kongo yang dijaga gorila.
Buku juga berarti strategi perang, denting pedang, derap kuda, badai debu. Cinta sekaligus dendam, di perang besar Baratayudha. Di mana Abimanyu tertancap oleh puluhan senjata pasukan Kurawa sedang Resi Bhisma terhujam oleh seribu anak panah Arjuna.
Buku juga adalah teka-teki penuh misteri. Di mana Robert Langdon berjalan, berlari, dengan waktu di malam buta, mencoba memecahkan kode rahasia lukisan-lukisan Leonardo Da Vinci. Buku berarti juga penguak tabir misteri. Seperti Poirot yang menelengkan mata untuk memberi kesempatan sel-sel kelabu di kepalanya untuk bekerja dalam membuat gambaran besar dari kepingan-kepingan puzzle.
Buku adalah petunjuk jalan ke kotak harta yang terkubur berabad-abad. Kotak harta yang sarat petuah tentang kebijakan, kebajikan dan kebijaksanaan. Seperti Syaikh munir al-Gotbhan yang menulis sejarah kehidupan Rasulullah dari sudut yang berbeda sama sekali. Sebuah perjalanan kehidupan yang kaya hikmah, pelajaran, panduan, kejutan dan ketakjuban baru di tiap tikungnya.
Buku adalah sebuah gerbang, portal ke dunia yang sama sekali lain. Dunia di mana ada Peri Rumah yang sibuk menyiapkan makanan untuk pesta penyambutan murid baru di Hogwarts, dan ada Hobbit bertugas menghancurkan sebuah cincin ke kawah berapi.
Buku, menurutku, tak hanya mengabarkan fakta akan dunia luar: Migrasi ikan, hibernasi beruang. strategi burung manyar dalam menarik pasangan. Buku juga mengundang kita untuk menikmati benak dan emosi manusia. Menyaksikan konflik dan dilema kehidupan anak manusia. Buku mengajak kita untuk jadi kontemplatif, berdiam sebentar mengamati drama dan tragedi dalam hidup manusia lain, entah fakta atau fiksi, dan melaluinya bercermin mematut hidup sendiri.
Tapi hati-hati, karena ketenangannya, buku juga berpotensi untuk menenggelamkan, seperti telaga dan pasir hisap. Seperti mantra avada kadavera.
Itulah membaca dan buku buatku. Sebuah petualangan. Maka, buku yang tidak bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan, dan buku yang tidak bisa memberikan perjalanan dan pengalaman baru tiap kali membacanya, buku yang tidak bisa dibaca berulang-ulang, menurut ku bukan buku yang layak dibaca.
Buku pertama yang menjadi favoritku adalah Menikmati Demokrasi dan Dari Gerakan ke Negara. Berasal dari Kumpulan kolom di Majalah Saksi dan Majalah Hidayatullah. Walau tak dimaksudkan untuk menjadi sebuah buku, tapi dari isinya tergambar sebuah uraian satu tema besar. Di mana setiap kolom terasa begitu koheren dan terstruktur dengan yang lain. Sehingga antara satu kolom dengan yang lainnya saling menopang dan mengisi. Buku tersebut berlatar kondisi Indonesia kontemporer dengan solusi kearifan masa kenabian. Anis Matta, sang penulis, mampu menterjemahkan sebuah konsep gerakan dakwah yang besar dalam tulisan yang sederhana dengan gayanya yang khas: tak banyak kata, dengan diksi terpilih, semua diracik dengan bumbu prosaik lincah dan segar. Sesedap Mencari Pahlawan Indonesia dan Serial Cinta-nya yang juga jadi favoritku.
Buku ke dua yang juga menjadi pavoritku adalah : Kuartet Pulau Buru : Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Membaca ke empat buku tersebut serasa dimasukkan dalam benak sang tokoh tapi juga ke setting tempat dan waktu cerita berlangsung. Pram mampu memaparkan sejarah dari sudut kacamata lain. Di sanalah memang kekuatan Pram, mampu menggambarkan keadaan tempat, peristiwa sejarah, emosi jiwa, dan karakter tokoh yang begitu kuat. Sampai sekarang, ini kasus untuk saya, saya masih merasa sosok Minke, sang protagonis, tokoh sentral dari novel di atas, pendiri Syarikat Islam, benar-benar pernah hidup di awal Abad duapuluh.
Jika Pram begitu kuat dalam cerita-cerita sejarah Indonesia, maka Ahmad Tohari hebat dalam penuturannya tentang alam. Dengan penanya, burung alap-alap, jangkrik, kodok, bentangan sawah, mampu memberikan arti tersendiri tentang makna kehidupan. Dan dengan penuh puitik Tohari menyampaikannya. Makanya saya sangat senang dengan Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk nya. Sambil menikmati alam dan budaya Masyarakat Banyumas berlatar masa pemberontakan PKI, kita juga diajak mengikuti kisah lenggak-lenggok hidup Srintil dari sejak kecil dalam mencari sejatinya kehidupan.
Buku di atas tak lengkap tanpa mengikutkan buku lain : Burung-burung Manyar Romo Mangun, Max Havelaar nya Multatuli. Habis gelap terbitlah terang-nya kartini. Setelah Revolusi Tak ada Lagi dan Tuhan dan Hal-hal yang tak pernah Selesai serta Catatan Pinggir nya (khusus Caping tidak bisa saya nikmati lewat buku, susah carinya!) Goenawan Mohamad. Manhaj Haroki Syaikh Munir Al-Gothban. Serta yang terakhir kumpulan puisi Mata Pisau-nya Sapardi Djoko Damono.
Jumlah buku koleksi : layak lah untuk di sebut perpustakaan pribadi. Walau setelah diteliti lagi, ternyata tak seimbang memang jenis buku yang ada.
Buku yang terakhir dibaca: Sang Musafir Mohammad Sobary, Serial Cinta-nya Anis Matta, Aku, Buku dan Sepotong Sajak Cinta Muhidin M Dahlan, Horeeluya..! Arswendo Atmowiloto, Rahasia Membutuhkan Kata Harry Aveling, dan yang belum kelar-kelar Pergulatan Intelektual di Masa Kegelisahan sebuah buku untuk mengenang seratus hari wafatnya Romo Mangun.
book list yang ada tahun ini: Nyanyi Sunyi seorang Bisu-nya Pram, Olenka- Budi darma, Catatan Pinggir 7 Goen, Madilong, Tan Malaka (ini buku-buku yang susah dicari). Yang lainnya ada Laskar Pelangi Andrea Hirata,
Buku yang terakhir di beli :Sang Musafir sama serial Cinta.
Buku yang paling berkesan dan sering di baca: yah...judul-judul pertama yang di atas tadi.
Itu buku buatku yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Sekarang, kalau ada waktu terluang, sudilah kiranya Kang izul, Akh Andrik, Mbak Maul, untuk meneruskannya. Dan monggo kita simak apa sebenarnya buku buat mereka.
Maaff ya kalau merasa di teror.
08 October 2008
Alhamdulillah, Saya Baik-Baik Saja.
Hari ini genap satu minggu saya di rumah orang tua, di Sukabumi. Satu tempat dimana dulu saya pernah tumbuh dengan tradisi-tradisinya untuk mengikat sebuah bantalan identitas. Tradisi-tradisi yang mungkin kini tanpa sadar sudah melekat pada diri dan menjadi sebuah identitas yang berlaku ketika hidup ditengah yang lain. Kembali kerumah berarti kesempatan untuk menjalin kembali identitas yang mungkin lepas.
Pulang kembali kerumah berarti kembali ketempat yang dulu pernah akrab sejak kecil. Lekuk-lekuk jalan, jembatan, dering telpon, pintu, pohon-pohon, pos kamling, kebun, sungai, masjid, aspal yang terkelupas, semua sudah terukir di bawah sadar dan semua menyimpan ceritanya masing-masing. Sehingga ketika saya kembali, dengan sendirinya alur cerita yang dulu pernah dibuat kini menyeruak tampak hadir di pelupuk mata. Rasa, bau, cerita, hadir kembali, mengapung memenuhi rongga kepala, bak film lama yang diputar kembali.
***
Selama seminggu itu, banyak teman dan saudara-saudaraku, di Sukabumi, bertanya bagaimana tentang kabar kuliah ku di Malang saat ini. Dan untuk memuaskan rasa penasaran atau hanya untuk menjawab pertanyaan mereka, biasanya aku jawab dengan : Alhamdulillah, baik-baik saja. Cukup. Bukan jawaban basa-basi. (Saya memang tak suka basa-basi. Jika terpaksapun harus berbasa-basi ketika bertemu kawan lama, maka saya akan awali dengan pengakuan saya ingin berbasa-basi dengan kawan tersebut. Dan sebuah obrolan yang sudah disadari dari awal oleh kedua pihak bahwa obrolannya adalah obrolan basa-basi, itu bukan obrolan basa-basi menurutku).
‘Alhamdulillah, baik-baik saja’. Sudah sangat cukup menggambarkan keadaanku saat ini.
Walaupun saya sadar, kata ‘baik-baik saja’ tersebut tak selalu menempatkan diri ini pada posisi yang diinginkan atau posisi yang diimpikan. Misalnya untuk lulus.
selalu saya mencoba belajar rumus tentang posisi hidup: ketika berdiri di puncak harapan ataupun berada di dasar jurang kehidupan. Belajar bertanya bahwa rencana yang terbaik buatku belum tentu baik bagi Yang Maha Mengatur Rencana. Walaupun bukan berarti aku duduk saja atau diam saja dan ‘nrimo-nrimo’ keadaan sekarang. Bukan! Bukan berarti pula aku tak punya pendirian yang seperti debu yang bergerak ke timur jika angin bertiup dari barat.
Hanya mencoba belajar rumus tadi dengan cara membuka ruang kemungkinan, bahwa rencana yang terbaik buatku saat ini, belum tentu terbaik buat tangan yang mengatur rencana tadi. Hanya memberi ruang untuk sebuah kesadaran bahwa ada tangan yang tak terlihat yang juga mengatur jalan hidupku, yang biasanya sering tak saya sadari kehadirannya. Entah karena mimpi yang bertumpuk atau ambisi yang berkarat di hati sehingga menghilangkan kepekaannya.
Maka jawaban “Alhamdulillah, baik-baik saja” adalah ungkapan yang (menurut saya) sederhana namun tersimpan ungkapan syukur sekaligus sabar di sana. Sukur karena bertemunya harapan dengan kenyataan. Dan sabar ketika dihadapkan dengan harapan yang belum mewujud kenyataan. “Alhamdulillah, baik-baik saja” adalah upaya menjaga kesadaran agar tetap intens. Apalagi buat saya yang sebentar-sebentar tampak ringkih, sebentar-sebentar mengeluh, dan kadang kehilangan gairah perjuangan. Maka “Alhamdulillah, baik-baik saja” adalah jawaban yang tidak mengada-ngada. Dan apa adanya.
Maka kalau ada yang bertanya lagi tentang kabarku.
Maka, akan aku jawab dengan : Alhamdulillah, aku baik-baik saja. Bukan dengan jawaban Luar biasa!, Dahshat!!, seperti saran trainer-trainer motivator.
______________________________________________
owalahhhh mbang-mbang... Ditanya kabar ae ko jawabe njlimet ngono.
Pulang kembali kerumah berarti kembali ketempat yang dulu pernah akrab sejak kecil. Lekuk-lekuk jalan, jembatan, dering telpon, pintu, pohon-pohon, pos kamling, kebun, sungai, masjid, aspal yang terkelupas, semua sudah terukir di bawah sadar dan semua menyimpan ceritanya masing-masing. Sehingga ketika saya kembali, dengan sendirinya alur cerita yang dulu pernah dibuat kini menyeruak tampak hadir di pelupuk mata. Rasa, bau, cerita, hadir kembali, mengapung memenuhi rongga kepala, bak film lama yang diputar kembali.
***
Selama seminggu itu, banyak teman dan saudara-saudaraku, di Sukabumi, bertanya bagaimana tentang kabar kuliah ku di Malang saat ini. Dan untuk memuaskan rasa penasaran atau hanya untuk menjawab pertanyaan mereka, biasanya aku jawab dengan : Alhamdulillah, baik-baik saja. Cukup. Bukan jawaban basa-basi. (Saya memang tak suka basa-basi. Jika terpaksapun harus berbasa-basi ketika bertemu kawan lama, maka saya akan awali dengan pengakuan saya ingin berbasa-basi dengan kawan tersebut. Dan sebuah obrolan yang sudah disadari dari awal oleh kedua pihak bahwa obrolannya adalah obrolan basa-basi, itu bukan obrolan basa-basi menurutku).
‘Alhamdulillah, baik-baik saja’. Sudah sangat cukup menggambarkan keadaanku saat ini.
Walaupun saya sadar, kata ‘baik-baik saja’ tersebut tak selalu menempatkan diri ini pada posisi yang diinginkan atau posisi yang diimpikan. Misalnya untuk lulus.
selalu saya mencoba belajar rumus tentang posisi hidup: ketika berdiri di puncak harapan ataupun berada di dasar jurang kehidupan. Belajar bertanya bahwa rencana yang terbaik buatku belum tentu baik bagi Yang Maha Mengatur Rencana. Walaupun bukan berarti aku duduk saja atau diam saja dan ‘nrimo-nrimo’ keadaan sekarang. Bukan! Bukan berarti pula aku tak punya pendirian yang seperti debu yang bergerak ke timur jika angin bertiup dari barat.
Hanya mencoba belajar rumus tadi dengan cara membuka ruang kemungkinan, bahwa rencana yang terbaik buatku saat ini, belum tentu terbaik buat tangan yang mengatur rencana tadi. Hanya memberi ruang untuk sebuah kesadaran bahwa ada tangan yang tak terlihat yang juga mengatur jalan hidupku, yang biasanya sering tak saya sadari kehadirannya. Entah karena mimpi yang bertumpuk atau ambisi yang berkarat di hati sehingga menghilangkan kepekaannya.
Maka jawaban “Alhamdulillah, baik-baik saja” adalah ungkapan yang (menurut saya) sederhana namun tersimpan ungkapan syukur sekaligus sabar di sana. Sukur karena bertemunya harapan dengan kenyataan. Dan sabar ketika dihadapkan dengan harapan yang belum mewujud kenyataan. “Alhamdulillah, baik-baik saja” adalah upaya menjaga kesadaran agar tetap intens. Apalagi buat saya yang sebentar-sebentar tampak ringkih, sebentar-sebentar mengeluh, dan kadang kehilangan gairah perjuangan. Maka “Alhamdulillah, baik-baik saja” adalah jawaban yang tidak mengada-ngada. Dan apa adanya.
Maka kalau ada yang bertanya lagi tentang kabarku.
Maka, akan aku jawab dengan : Alhamdulillah, aku baik-baik saja. Bukan dengan jawaban Luar biasa!, Dahshat!!, seperti saran trainer-trainer motivator.
______________________________________________
owalahhhh mbang-mbang... Ditanya kabar ae ko jawabe njlimet ngono.
05 October 2008
yang terlintas
Apakah yang terlintas di benak seorang aparat pemerintah tentang rakyat??
apa yang terlintas di benaknya keika menghadiri rapat-rapat pimpinan? ketika tampil di layar kaca?
Korban tak terhindarkan? Tumbal kebijakan? Segumpal daging? Peluang usaha? Angka statistik?
Target pembodohan? Sapi perahan?
Apakah yang terlintas di benak wakil rakyat ketika bicara rakyat??
apa yang terlintas di benaknya keika sidang pembahasan undang-undang? ketika reses?
Peluang suara? Target pembodohan? Senjata kampanye? Stempel orasi? Pengerahan massa? Batu loncatan? Jalan karir? Sumber finansial?
Sekarang apa yang terlintas di benak anda ketika bicara wakil rakyat dan aparat pemerintahan??
apa yang terlintas di benaknya keika menghadiri rapat-rapat pimpinan? ketika tampil di layar kaca?
Korban tak terhindarkan? Tumbal kebijakan? Segumpal daging? Peluang usaha? Angka statistik?
Target pembodohan? Sapi perahan?
Apakah yang terlintas di benak wakil rakyat ketika bicara rakyat??
apa yang terlintas di benaknya keika sidang pembahasan undang-undang? ketika reses?
Peluang suara? Target pembodohan? Senjata kampanye? Stempel orasi? Pengerahan massa? Batu loncatan? Jalan karir? Sumber finansial?
Sekarang apa yang terlintas di benak anda ketika bicara wakil rakyat dan aparat pemerintahan??
03 October 2008
Rindu Malang
Abu Semeru yang tercurah dari langit. Debu yang turun melayang lemah, hampa dan ragu namun merebak di sudut-sudut kota.
Teman-teman yang tercerai berai mengepak sayap sendiri-sendiri menuju mimpi masing-masing. Gang-gang. Rumah-rumah.
Warung-warung malam.
Geliat hidup.
Manusia yang terpanggang jalanan yang panas dan terjerang mentari yang terik. Keringat yang mengalirr menderas tak henti bagai sungai Kali Brantas yang membelah Malang.
Bangga, sedih, kecewa, adalah Malang bagiku.
Tempat aku berjalan setapak demi setapak dalam perjalanan menjadi diri sendiri. Tempat aku sering terjatuh dan mencoba terus untuk bisa memungut pelajaran darinya.
Mengingat semua hari dan kenangan yang pernah terlalui bersama. Futsal. Berkendara malam-malam. Kampus dan komsat tempat kami tertatih-tatih belajar menerima tanggungjawab bersama, segala salah paham yang pernah mewarnai, segala kekesalan dan pengampunan yang pernah mengambil tempat dalam hidup kami adalah pelajaran seribu SKS (Sistem Kredit Semester) bagiku.
Jalan MT Haryono. Gajayana. Sumbersari. Veteran. Kerto-kerto. Toko buku. Perempatan-perempatan. Berdenyut, meruas di jalan nadiku.
Segala harap, segala rindu, segala kecewa, segala sedih, segala cinta, berdetak terkecap dalam hati.
Dan ketika senja mulai pergi hari ini di Sukabumi, entah cemas entah harap, yang membuatku teringat tentang Malang.
Tapi yang pasti aku akan kembali ke Malang.
Karena kerja belum selesai. Dan janji belum tunai.
Buat Catur, Toto, Danny, Fajar.
Yang lainnya ingin saya sebut dalam hati.
______________________________________
Kenapa ?? disaat-saat seperti ini aku teringat terus sesuatu... apa ya?? Saat berkunjung ke handai taulan. Saat ngerjakan pemetaan fishing ground ikan tuna. Saat ngitungin statistik produksi perikanan Pelabuhanratu. Saat leyeh-leyeh, saat menyusuri jalan, terus teringat aku sesuatu. Seingatku dulu aku pernah seperti ini. Pas pertama-pertama liburan kuliah dan meninggalkan Malang.
Teman-teman yang tercerai berai mengepak sayap sendiri-sendiri menuju mimpi masing-masing. Gang-gang. Rumah-rumah.
Warung-warung malam.
Geliat hidup.
Manusia yang terpanggang jalanan yang panas dan terjerang mentari yang terik. Keringat yang mengalirr menderas tak henti bagai sungai Kali Brantas yang membelah Malang.
Bangga, sedih, kecewa, adalah Malang bagiku.
Tempat aku berjalan setapak demi setapak dalam perjalanan menjadi diri sendiri. Tempat aku sering terjatuh dan mencoba terus untuk bisa memungut pelajaran darinya.
Mengingat semua hari dan kenangan yang pernah terlalui bersama. Futsal. Berkendara malam-malam. Kampus dan komsat tempat kami tertatih-tatih belajar menerima tanggungjawab bersama, segala salah paham yang pernah mewarnai, segala kekesalan dan pengampunan yang pernah mengambil tempat dalam hidup kami adalah pelajaran seribu SKS (Sistem Kredit Semester) bagiku.
Jalan MT Haryono. Gajayana. Sumbersari. Veteran. Kerto-kerto. Toko buku. Perempatan-perempatan. Berdenyut, meruas di jalan nadiku.
Segala harap, segala rindu, segala kecewa, segala sedih, segala cinta, berdetak terkecap dalam hati.
Dan ketika senja mulai pergi hari ini di Sukabumi, entah cemas entah harap, yang membuatku teringat tentang Malang.
Tapi yang pasti aku akan kembali ke Malang.
Karena kerja belum selesai. Dan janji belum tunai.
Buat Catur, Toto, Danny, Fajar.
Yang lainnya ingin saya sebut dalam hati.
______________________________________
Kenapa ?? disaat-saat seperti ini aku teringat terus sesuatu... apa ya?? Saat berkunjung ke handai taulan. Saat ngerjakan pemetaan fishing ground ikan tuna. Saat ngitungin statistik produksi perikanan Pelabuhanratu. Saat leyeh-leyeh, saat menyusuri jalan, terus teringat aku sesuatu. Seingatku dulu aku pernah seperti ini. Pas pertama-pertama liburan kuliah dan meninggalkan Malang.
buat Suaidi
Postingan ini sebenarnya tak bertanggal hari ini. Tapi karena seminggu kemarin disibukkan dengan persiapan mudik dan mudik serta harus kerja extra, jadi seminggu kemarin bener-bener gak sempet posting apapun. Maka terposting-lah hari ini.
Hari ini sobatku ulang tahun. Suaidi Bakhtiar, 24 Tahun sekarang. Pertama kali mengenalnya sekitar tahun 2005-an. Kami cukup dekat karena kami pernah tinggal bareng satu kontrakan, Jl Gajayana no 577 b, di belakang Sardo..pernah ngerjain ini itu bareng-bareng...pernah cerita tentang petualangan bersama...
Kalem. lumayan tinggi dan besar. Lahir di Banyuwangi. Pemeluk teguh. Aktor mumpuni. Humoris. Orator ulung. Cerdas dan cermat. Pecinta buku, yang koleksi bukunya bertumpuk di lemarinya. Cita-citanya ingin punya ponpes (kalau ga berubah).
Bisa diajak bicara tentang banyak hal. Hampir semuanya... dari Agama ke sejarah ke pendidikan ke buku ke kuliner ke internet ke blog ke musik ke teater ke budaya ke kebudayaan ke film ke Indonesia ke keIndonesiaan ke perang ke manusia ke kemanusiaan ke berenang ke organisasi ke mimpi ke puisi ke cinta ke mana-mana lah... Siap dengerin unek-unek yang ga berujung. Dialah salah satu teman yang paling asyik kalau diajak diskusi, terbuka akan pendapat yang segimanapun berbedanya. Sabar dan pinter mainin ‘kartu’ nya dalam adu pendapat, tapi tetep ga kekeh dan nggak ada pretensi untuk merasa paling bener dan paling tahu apalagi sampai memonopoli kebenaran.
Tak menggurui saat memberikan arahan.
Walau kami sama-sama pecinta buku dan seni tapi kami memiliki ketertarikan dan minat yang berbeda di dua hal tersebut. Ia suka buku agama sedang saya seneng banget sama novel dan sastra. Ia suka teater dan entreupneeur saya lebih seneng (belajar) menulis dan sepak bola. Makanya, ketika saya bangga2nya karena telah hatamin buku Musashi dan Taiko-nya Eiji Yosikawa yang setebel bantal, Ia sama sekali tak terkesan. Ia lebih menghargai buku yang (walaupun tipis namun) dapat mendekatkan pembacanya kepada Allah.
Namun pada akhirnya ada juga buku yang sama-sama kami senangi : buku-bukunya Anis Matta. Tema-tema tulisan di buku-bukunya (PM A21, MPI, DGKN, Mendem, Serial Cintanya yang waktu itu masih digarap di Majalah tarbawi), sering menjadi topik pembicaraan kami di sepanjang hari bahkan mungkin terbawa disepanjang minggu. Mungkin karena kesukaan itu pula telah merubah langgam kami bicara, kerangka kami berpikir dan mungkin tercetak dalam bagaimana cara kami menulis. Entahlah.
Salah satu yang teringat lekat dalam benak tentang Mas yang satu ini adalah gaya kepememimpinannya. Salah satu gaya khas-nya memimpin teingat jika kami di komisariat UB berada dalam situasi genting dengan masalah bejibun tak tertangani.
Ia nggak banyak menyerahkan persoalan ke floor. Sebaliknya, ia datang dengan solusi jadi, dan solusi jadi itulah yang kemudian di floor kan dengan argumen sekeras baja. Bukan karena logika argumennya, tapi lebih pada cara mengemukakan argumennya itu. Seperti adigium : the medium is the message. Jadi kalau mediumnya rigid, ya orang kemudian menangkap message argumennya sebagai sesuatu yang rigid.
Beda banget sama saya. Saya ini sok-sok an demokratis dan egaliter. Biasa memulai sesuatu dari masalah. Me-list masalah, lalu, siapa yang punya solusi silahkan bicara, pengennya kelihatan demokratis gitu. Meski kalau dipikir-pikir lagi, goblok juga ngelempar masalah ke orang-orang yang tiap harinya diajar mengunyah masalah. Seperti ngelempar irisan daging ke kawanan srigala... pada berebut daging yang cuma sekerat. Ribut, riuh bukan main. Cakar sana gigit sini. Injak sana dorong sini. Daging hancur terbagi banyak. Tak ada yang benar puas.. Malah tersisa goresan-goresan luka terkena cakar dan taring. Bodoh.
Tapi, dari semua itu, yang bikin lebih kami deket satu sama lain –yang ga tahu kenapa- adalah kami terbuka satu sama lain. Nggak ada perasaan yang di kubur saat ngomong dengannya. Kalau ada sesuatu yang aku nggak suka dengan apa yang ia perbuat atau lakuin, aku akan ngomong. Di depan nya langsung, juga sebaliknya (semoga..).
Keterbukaan ini yang mungkin bikin kami deket. Dan dari semua itu, yang pasti, dari beliau ini saya belajar tentang sahabat. Bahwa menjadi seorang sahabat bukan cuma mengusahakan kenyamanan semata, namun juga saling mengingatkan akan panggilan Yang Maha .. biarpun itu mungkin berarti membawa sang sahabat ke situasi yang tak menyenangkan.
Mungkin lebih. Mungkin saya menginginkan lebih. Atau mungkin tidak sama sekali.
Selebihnya tak aku sampaikan.
Mungkin malah ada baiknya beberapa hal-hal tak terkatakan.
Ya...Hari ini ia ulang tahun, walau masih sama-sama di Malang, kami sudah jarang bertatap muka..
Tak ada yang bisa saya berikan di hari ulang tahunnya. Hanya do’a : semoga Allah terus merestui dan memudahkan setiap langkahnya. Selamanya.
Semoga terang pengertian dan pemahaman yang dari-Nya saja yang menjadi lentera kita membangun satu dua persahabatan dalam hidup yang sebentar ini.
Anda ingin lebih kenal beliau, saya saranin untuk langsung saja kunjungi blognya, di jamin deh ga rugi. Kalau pas kesana ditanya. Bilang saja disuruh Bambang tris gituhhh...
Karena momennya juga pas.
Saya ucapin juga :
Minal Aidin wal fa izin.
Taqobbalallahu minna wa minkum. Taqobbalyaa kariim.
Buat semuanya yang sering ngunjungin, iseng atau nyasar ke Blog ini.
Hari ini sobatku ulang tahun. Suaidi Bakhtiar, 24 Tahun sekarang. Pertama kali mengenalnya sekitar tahun 2005-an. Kami cukup dekat karena kami pernah tinggal bareng satu kontrakan, Jl Gajayana no 577 b, di belakang Sardo..pernah ngerjain ini itu bareng-bareng...pernah cerita tentang petualangan bersama...
Kalem. lumayan tinggi dan besar. Lahir di Banyuwangi. Pemeluk teguh. Aktor mumpuni. Humoris. Orator ulung. Cerdas dan cermat. Pecinta buku, yang koleksi bukunya bertumpuk di lemarinya. Cita-citanya ingin punya ponpes (kalau ga berubah).
Bisa diajak bicara tentang banyak hal. Hampir semuanya... dari Agama ke sejarah ke pendidikan ke buku ke kuliner ke internet ke blog ke musik ke teater ke budaya ke kebudayaan ke film ke Indonesia ke keIndonesiaan ke perang ke manusia ke kemanusiaan ke berenang ke organisasi ke mimpi ke puisi ke cinta ke mana-mana lah... Siap dengerin unek-unek yang ga berujung. Dialah salah satu teman yang paling asyik kalau diajak diskusi, terbuka akan pendapat yang segimanapun berbedanya. Sabar dan pinter mainin ‘kartu’ nya dalam adu pendapat, tapi tetep ga kekeh dan nggak ada pretensi untuk merasa paling bener dan paling tahu apalagi sampai memonopoli kebenaran.
Tak menggurui saat memberikan arahan.
Walau kami sama-sama pecinta buku dan seni tapi kami memiliki ketertarikan dan minat yang berbeda di dua hal tersebut. Ia suka buku agama sedang saya seneng banget sama novel dan sastra. Ia suka teater dan entreupneeur saya lebih seneng (belajar) menulis dan sepak bola. Makanya, ketika saya bangga2nya karena telah hatamin buku Musashi dan Taiko-nya Eiji Yosikawa yang setebel bantal, Ia sama sekali tak terkesan. Ia lebih menghargai buku yang (walaupun tipis namun) dapat mendekatkan pembacanya kepada Allah.
Namun pada akhirnya ada juga buku yang sama-sama kami senangi : buku-bukunya Anis Matta. Tema-tema tulisan di buku-bukunya (PM A21, MPI, DGKN, Mendem, Serial Cintanya yang waktu itu masih digarap di Majalah tarbawi), sering menjadi topik pembicaraan kami di sepanjang hari bahkan mungkin terbawa disepanjang minggu. Mungkin karena kesukaan itu pula telah merubah langgam kami bicara, kerangka kami berpikir dan mungkin tercetak dalam bagaimana cara kami menulis. Entahlah.
Salah satu yang teringat lekat dalam benak tentang Mas yang satu ini adalah gaya kepememimpinannya. Salah satu gaya khas-nya memimpin teingat jika kami di komisariat UB berada dalam situasi genting dengan masalah bejibun tak tertangani.
Ia nggak banyak menyerahkan persoalan ke floor. Sebaliknya, ia datang dengan solusi jadi, dan solusi jadi itulah yang kemudian di floor kan dengan argumen sekeras baja. Bukan karena logika argumennya, tapi lebih pada cara mengemukakan argumennya itu. Seperti adigium : the medium is the message. Jadi kalau mediumnya rigid, ya orang kemudian menangkap message argumennya sebagai sesuatu yang rigid.
Beda banget sama saya. Saya ini sok-sok an demokratis dan egaliter. Biasa memulai sesuatu dari masalah. Me-list masalah, lalu, siapa yang punya solusi silahkan bicara, pengennya kelihatan demokratis gitu. Meski kalau dipikir-pikir lagi, goblok juga ngelempar masalah ke orang-orang yang tiap harinya diajar mengunyah masalah. Seperti ngelempar irisan daging ke kawanan srigala... pada berebut daging yang cuma sekerat. Ribut, riuh bukan main. Cakar sana gigit sini. Injak sana dorong sini. Daging hancur terbagi banyak. Tak ada yang benar puas.. Malah tersisa goresan-goresan luka terkena cakar dan taring. Bodoh.
Tapi, dari semua itu, yang bikin lebih kami deket satu sama lain –yang ga tahu kenapa- adalah kami terbuka satu sama lain. Nggak ada perasaan yang di kubur saat ngomong dengannya. Kalau ada sesuatu yang aku nggak suka dengan apa yang ia perbuat atau lakuin, aku akan ngomong. Di depan nya langsung, juga sebaliknya (semoga..).
Keterbukaan ini yang mungkin bikin kami deket. Dan dari semua itu, yang pasti, dari beliau ini saya belajar tentang sahabat. Bahwa menjadi seorang sahabat bukan cuma mengusahakan kenyamanan semata, namun juga saling mengingatkan akan panggilan Yang Maha .. biarpun itu mungkin berarti membawa sang sahabat ke situasi yang tak menyenangkan.
Mungkin lebih. Mungkin saya menginginkan lebih. Atau mungkin tidak sama sekali.
Selebihnya tak aku sampaikan.
Mungkin malah ada baiknya beberapa hal-hal tak terkatakan.
Ya...Hari ini ia ulang tahun, walau masih sama-sama di Malang, kami sudah jarang bertatap muka..
Tak ada yang bisa saya berikan di hari ulang tahunnya. Hanya do’a : semoga Allah terus merestui dan memudahkan setiap langkahnya. Selamanya.
Semoga terang pengertian dan pemahaman yang dari-Nya saja yang menjadi lentera kita membangun satu dua persahabatan dalam hidup yang sebentar ini.
Anda ingin lebih kenal beliau, saya saranin untuk langsung saja kunjungi blognya, di jamin deh ga rugi. Kalau pas kesana ditanya. Bilang saja disuruh Bambang tris gituhhh...
Karena momennya juga pas.
Saya ucapin juga :
Minal Aidin wal fa izin.
Taqobbalallahu minna wa minkum. Taqobbalyaa kariim.
Buat semuanya yang sering ngunjungin, iseng atau nyasar ke Blog ini.
23 September 2008
suatu saat...
Suatu saat tiba aku di suatu momen. Ketika langkah kaki melenggang. Kepala mendongak. Saat berdiri tegak di bukit hidup dan menatap remeh lembah-lembah takdir. Menyombongkan diri. Seakan nasib berada di genggaman tangan. Seakan segala penjuru angin terkuasai. Berasyik masyuk dengan segala air, dan bermain dengan segala angin.
Sampai suatu kali. Akhirnya terhempas aku ke karang terjal. Tersungkur. Patah. Robek. Putus. Menemukan diri ternyata tak lebih berdaya daripada buih diamuk badai. Berkumpul untuk kembali hancur. Dan kembali hancur.
Melihat segala pedih dosa dan akhirnya menyeret diri kembali ke altar pengampunan.
Menangis lemah dihadapNya. Sadari betapa manusia dalam diriku tak lebih dari seorang pengecut. Pendosa. Yang kembali tersungkur di kaki-Nya, memohon ampunan-Nya, saat diri sudah terantuk batu cadas. tak berbentuk.
Selalu. Selalu. Dan selalu. Dan selalu begitu.
aku menghampiriNya saat diri telah remuk. Tinggal sisa.
Namun tak bosan Ia mengampuni. Memaafkan kembali hambaNya.
Ia beri kembali aku bentuk. Kesadaran. Penglihatan. Ia kuatkan kembali kakiku. Ia kumpulkan aku.. beri cahaya. Segarkan aku kembali. Sampai aku bisa berjalan dan siap khianati Ia lagi....
Maka akupun berjalan lagi dengan kepala lebih mendongak. Lebih sombong.
Sampai kembali terhempas aku lebih keras. Lebih sakit. Lebih patah. Lebih hancur..
Ah, betapa bodoh...
betapa bodoh.
Ya Allah berkati aku.
Di setiap titik dalam belajar menjadi diri sendiri.
Sampai suatu kali. Akhirnya terhempas aku ke karang terjal. Tersungkur. Patah. Robek. Putus. Menemukan diri ternyata tak lebih berdaya daripada buih diamuk badai. Berkumpul untuk kembali hancur. Dan kembali hancur.
Melihat segala pedih dosa dan akhirnya menyeret diri kembali ke altar pengampunan.
Menangis lemah dihadapNya. Sadari betapa manusia dalam diriku tak lebih dari seorang pengecut. Pendosa. Yang kembali tersungkur di kaki-Nya, memohon ampunan-Nya, saat diri sudah terantuk batu cadas. tak berbentuk.
Selalu. Selalu. Dan selalu. Dan selalu begitu.
aku menghampiriNya saat diri telah remuk. Tinggal sisa.
Namun tak bosan Ia mengampuni. Memaafkan kembali hambaNya.
Ia beri kembali aku bentuk. Kesadaran. Penglihatan. Ia kuatkan kembali kakiku. Ia kumpulkan aku.. beri cahaya. Segarkan aku kembali. Sampai aku bisa berjalan dan siap khianati Ia lagi....
Maka akupun berjalan lagi dengan kepala lebih mendongak. Lebih sombong.
Sampai kembali terhempas aku lebih keras. Lebih sakit. Lebih patah. Lebih hancur..
Ah, betapa bodoh...
betapa bodoh.
Ya Allah berkati aku.
Di setiap titik dalam belajar menjadi diri sendiri.
17 September 2008
Tolong saya.....
tolongg saya....
tergagap...terbata..terisak...tersedak...mereka pagi itu, di depan pintu seseorang yang dapat memberi uang untuk sesuap nasi.
tolonnng saya, Pak..
terdesak...terperangkap...mereka pagi itu, di tengah lautan manusia yang berebut uang untuk sepiring makanan.
tolong saya, Bu...
terinjak...tergilas...terkapar...tergeletak mereka siang itu, di bawah terik, diantara debu dan kulit, di genangan keringat dan air mata.
dan kitapun dapat membaca bahwa anggota negeri ini ternyata masih sangat jauh dari sejahtera.
di tengah terbolak-baliknya sendi kehidupan, di tengah nyeri akan ketidakmampuan kita untuk dapat bersama mengelola sebuah kehidupan yang layak bagi sesama.
semoga kita belum jatuh lebih rendah dari manusia.
janji perbaikan semoga tidak berhenti sampai di makam duapuluh satu korban tragedi pasuruan, tapi berjangkit disetiap kita yang mendengarnya, untuk kembali menata sebuah perikehidupan untuk semua. untuk kembali belajar tentang manusia dan kemanusiaan.
::teriring belasungkawa::
bukan karena miskin kau terinjak
bukan karena fakir kau terkapar
tapi di pundak-pundak ini
tak terbeban sakit dan dukamu
tergagap...terbata..terisak...tersedak...mereka pagi itu, di depan pintu seseorang yang dapat memberi uang untuk sesuap nasi.
tolonnng saya, Pak..
terdesak...terperangkap...mereka pagi itu, di tengah lautan manusia yang berebut uang untuk sepiring makanan.
tolong saya, Bu...
terinjak...tergilas...terkapar...tergeletak mereka siang itu, di bawah terik, diantara debu dan kulit, di genangan keringat dan air mata.
dan kitapun dapat membaca bahwa anggota negeri ini ternyata masih sangat jauh dari sejahtera.
di tengah terbolak-baliknya sendi kehidupan, di tengah nyeri akan ketidakmampuan kita untuk dapat bersama mengelola sebuah kehidupan yang layak bagi sesama.
semoga kita belum jatuh lebih rendah dari manusia.
janji perbaikan semoga tidak berhenti sampai di makam duapuluh satu korban tragedi pasuruan, tapi berjangkit disetiap kita yang mendengarnya, untuk kembali menata sebuah perikehidupan untuk semua. untuk kembali belajar tentang manusia dan kemanusiaan.
::teriring belasungkawa::
bukan karena miskin kau terinjak
bukan karena fakir kau terkapar
tapi di pundak-pundak ini
tak terbeban sakit dan dukamu
14 September 2008
Bicara tentang kritik
Kritik memang dibutuhkan dimanapun kita berada untuk meningkatkan kualitas kehidupan.. Tanpa kritik dalam ilmu pengetahuan, kita tak tahu lagi mengapa seorang ilmuwan banyak dipuja-puja sekalipun hasil penelitiannya tidak ada. Tanpa kritik seorang selebriti tiba-tiba menjadi intelektual tanpa kerja apapun yang ada artinya secara intelektual. Tanpa kritik kita juga tidak tahu apa keberhasilan seorang politikus.
Banyak orang bicara tentang kritik yang membangun dan kritik yang destruktif. Padahal kritik yang membangun dan meruntuhkan adalah sebuah pilihan. Kritik akan membangun jika hanya mungkin bila kita bersedia menjadikannya bahan bangunan dan tidak menganggapnya racun dalam makanan.
Tidak ada kritik yang dengan sendirinya membangun sama seperti tidak ada kritik yang dengan sendirinya menghancurkan.
Kritik ibarat hidangan di atas meja. Yang menelannya akan kenyang dan yang menghindarinya akan terus-menerus mengutuk kelaparan.
Etika mengkritik...
Jangan sampai dilupakan, semangat mengkritik adalah semangat mempelajari dengan sungguh-sungguh, mencintai dan kemudian menyatakan bahwa apa yang dicintai itu bisa lebih baik apabila beberapa syarat lain dipenuhi.
Dan hal tersebut yang sering dilupakan oleh para peng-kritik jalanan -seperti saya contohnya-. intropeksi diri sendiri itu yang sering dilupakan pengkiritik otodidak (lha mau kritik ae moso mesti sinao... salah satu kelebihan manusia kan dapat otodidak dalm hal seperti ni: mengkritik hehe..) Apa sebabnya, saya sendiri tidak tahu. Entah atas prasangka pribadi yang menumpuk atau yah...saya ga tahu... (kalau saya tulis berarti saya tau dong).
Bolehkah kita mengkritik orang lain? Atau apa saja…?
Tentu saja boleh, sangat-sangat boleh. Asal saja kita bersedia bahwa dalam melakukannya kita juga akan mengkrtik diri sendiri. Dan bersedia memperbaiki bila ternyata kita juga bagian dari sasaran kritik... bukan hanya berharap jawaban perbaikan dari hal yang dikritisi. Walaupun harapan terbesar peng-kritik adalah jawaban perbaikan .
Kalau kata Samuel Mulya, pengasuh kolom Parodi di Kompas, edisi Muna (klo ga salah), hariii gini ngelepas rumah di Menteng… beraaattt….. mbooo!!
:: Dari yang suka ngritik tapi malesss banget intropeksi saat mengkritik. tuambbah maless klo kena kritik::
lha kalo sampeyan di kritik gimana???
Banyak orang bicara tentang kritik yang membangun dan kritik yang destruktif. Padahal kritik yang membangun dan meruntuhkan adalah sebuah pilihan. Kritik akan membangun jika hanya mungkin bila kita bersedia menjadikannya bahan bangunan dan tidak menganggapnya racun dalam makanan.
Tidak ada kritik yang dengan sendirinya membangun sama seperti tidak ada kritik yang dengan sendirinya menghancurkan.
Kritik ibarat hidangan di atas meja. Yang menelannya akan kenyang dan yang menghindarinya akan terus-menerus mengutuk kelaparan.
Etika mengkritik...
Jangan sampai dilupakan, semangat mengkritik adalah semangat mempelajari dengan sungguh-sungguh, mencintai dan kemudian menyatakan bahwa apa yang dicintai itu bisa lebih baik apabila beberapa syarat lain dipenuhi.
Dan hal tersebut yang sering dilupakan oleh para peng-kritik jalanan -seperti saya contohnya-. intropeksi diri sendiri itu yang sering dilupakan pengkiritik otodidak (lha mau kritik ae moso mesti sinao... salah satu kelebihan manusia kan dapat otodidak dalm hal seperti ni: mengkritik hehe..) Apa sebabnya, saya sendiri tidak tahu. Entah atas prasangka pribadi yang menumpuk atau yah...saya ga tahu... (kalau saya tulis berarti saya tau dong).
Bolehkah kita mengkritik orang lain? Atau apa saja…?
Tentu saja boleh, sangat-sangat boleh. Asal saja kita bersedia bahwa dalam melakukannya kita juga akan mengkrtik diri sendiri. Dan bersedia memperbaiki bila ternyata kita juga bagian dari sasaran kritik... bukan hanya berharap jawaban perbaikan dari hal yang dikritisi. Walaupun harapan terbesar peng-kritik adalah jawaban perbaikan .
Kalau kata Samuel Mulya, pengasuh kolom Parodi di Kompas, edisi Muna (klo ga salah), hariii gini ngelepas rumah di Menteng… beraaattt….. mbooo!!
:: Dari yang suka ngritik tapi malesss banget intropeksi saat mengkritik. tuambbah maless klo kena kritik::
lha kalo sampeyan di kritik gimana???
06 September 2008
kata-kata yang kau susun rapi
26 August 2008
Terjagaku pada hampa

Malam menyelimut. Di luar gelap, dingin pula. Hari ini angin memeluk Malang sepanjang hari. Sudah sejak tadi Sholat Isya aku duduk di depan layar monitor yang berkedip-kedip. Pukul dua belas lebih sebelas menit sekarang. Tak penuh konsentrasiku hari ini. Tuts keyboard komputer sering tak tersentuh oleh jemariku. Mencoba membaca namun makna, pemahaman tak mampir di sudut tempatku duduk hari ini. Laporan-laporan skripsi, buku, paper, masih menumpuk tak tertata disekitarku.
Kubuka winamp.. random. Play. Intro nya here with me Dido segera memenuhi kamar...Tak menginspirasi. Tak ada makna dalam diamku. Kuburu makna dalam diriku. Sia-sia. Tak tercipta suatu dalam renungku. Kosong.
Benakku masih bermain kesana kemari. Bak burung kenari yang bermain-main di ranting tua. Burung kenari yang lembut bulu, indah warna, serta merdu suara seakan menginagatkanmu akan sesuatu. Sesuatu yang tak ada disini.
Di luar sana, daun-daun meliuk menyapa diterpa angin. Kuteguk segelas air putih. Makna masih belum singgah disadarku. Here with me nya Dido hampir selesai... ”And I won’t go. I wonn’t sleep. I can’t breathe..”
tetap tak menginspirasi.
Di taksbar, file word ”bab empat” menggoda, memaksa, minta di’maximize’. Tak kuhirau. Sebuah kerja besar terjadwalakan harus selesai sebelum liburan lebaran nanti, namun tak ada bara yang menyala demi mereka. Hampa.
Setelah empat jam lebih memaksakan diri duduk disini, aku sadar dan menyerah. Aku lelah.
Dan sebelum semuanya tunai. Biar kutuntaskan dan kunikmati dulu dingin sunyi malam ini.
Ya Allah,
My Lord...
Help me.
Malang sebelum Ramadhan
ilustrai di atas saya contek dari sini
25 August 2008
Pertamina untung, Bangsa Buntung

Ini tulisan lama yang belum sempat saya posting. Karena hari2 ini momen nya pas banget, makanya saya posting saja sekarang. Setelah di update tentunya!
Mahal dan langka. sudah mahal, langka pula!. Itulah yang kerap ditemui dari barang-barang yang diproduksi dan atau dijajakan oleh pertamina. Mulai dari Bahan bakar jenis minyak (BBM) seperti minyak tanah, bensin, solar, sampai Bahan bakar jenis gas macam elpiji.
saya (juga anda?, mungkin) bukan pengguna langsung produk yang diurus oleh pertamina seperti minyak tanah (mitan), elpiji atau bensin (soalnya kompor sy g punya, motor pun tiada). Tapi, yang pasti saya tahu, bahwa dari mitan dan elpiji tersebutlah puluhan juta dapur rumah tetap bisa ngebul, dan orang macam saya (anak kos-an yang tak punya kompor dan motor) masih bisa makan diwarung-warung kecil dengan harga murah.
Dahulu, pada sebuah titikmangsa, dengan rasionalisasi bahwa APBN kita banyak terserap pada minyak tanah yang jumlahnya signifikan, pemerintah meluncurkan program konversi minyak tanah ke gas. Tujuannya yaitu untuk mengganti pola konsumsi masyarakat dari mitan ke gas, dengan cara bertahap mengurangi distribusi minyak tanah bersubsidi sambil menyalurkan kompor gas dan tabung elpiji bersubsidi ukuran 3 kilo untuk masyarakat kecil.
Sekarang, setelah program konversi mitan ke gas berjalan (dengan sempoyongan), maka hampir dipastikan setiap rumah tangga di perkotaan menggunakan gas elpiji, bukan lagi minyak tanah. Dan setelah hampir semuanya tergantung kebutuhan akan gas elpiji, pertamina dengan seenak perutnya menaikkan harga gas elpiji ukuran 12 kg. (pinter banget nih pertamina, dasar otak monopoli VOC, otak bandar, otak penjajah!!)
Tentu bukan kapasitas saya untuk menganalisis baik apa buruk, berhasil apa tidak program konversi tersebut. Bukan kapasitas saya pula untuk membahas teori2 ekonomi makro ataupun mikro yang sering dijadikan tameng oleh pertamina untuk menaikkan harga BBM/elpiji (yang seenak udelnya). Untuk soal “meng-analisa” tersebut rasanya ga kurang pakar, wakil pemerintah, aleg kita, yang bisa membahasnya dan lebih kompeten. (meskipun saya ragu juga ama anggota2 DPR. kemarin rame2 ributin hak interpelasi yang akhirnya bikin pansus. Eh... Udah jadi pansusnya sampai sekarang ga kedengeran kerjanya.... apa udah kenyang y dicekoki duit minyak pertamina?? Atau Cuma akal2an DPR aja untuk keluarin dana anggaran kali y??). Saya cuma ingin menuliskan lintasan pikiran ketika membaca gas harga gas elpiji naik. Aku Cuma ingin menuliskan lintasan pertanyaan2 yang menghantam benak awamku melihat tingkah pertamina.
***
Mahal dan langka. Itu kata2 yang menghantam-hantam dalam kepalaku.
Dalam teori ekonomi (saya sempat mengenal) istilah demand and suply atau pasokan dan permintan. Barang yang harganya diserahkan dalam mekanisme pasar pasti akan terkena dampak teori ini. Pasokan yang tidak sebanding dengan permintaan akan berpengaruh terhadap harga. Jika pasokan lebih tinggi dari permintaan harga turun dan begitu sebaliknya.
Tapi berbeda ceritanya jika barang tersebut adalah barang yang dikelola sendiri (dimonopoli ?) oleh pemerintah tanpa campur tangan dari pihak lain serta kebal terhadap mekanisme pasar. Berbeda ceritanya bila dalam pendistribusinya-pun mendapatkan perlakuan khusus dari undang-undang. Maka hukum pasokan dan permintaan harusnya tidak berpengaruh terhadap harga barang tersebut.
Maka adalah aneh dan sangat-sangat aneh bila kemudian kita masih menemukan BBM/elpiji yang sudah mahal, justru kemudian menjadi langka. Padahal pertamina harusnya tahu berapa ancer-ancer jumlah pasokan agar tidak langka.
Bila itu masih terjadi, maka (bagi saya) itu adalah sebuah kegagalan. Kegagalan dari Pertamina (dan juga kegagalan dari Pemerintah). Dan dalam kasus ini “kegagalan” artinya bukan “keberhasilan yang tertunda” seperti yang sering diteriakkan sama trainer2 dalam pelatihan. Dalam hal ini kegagalan berarti kebodohan yang terpelihara. Karena bukan saat ini saja BBM menjadi langka. Bukan saat ini saja elpiji susah dicari.
Makanya ketika sering lihat iklan pertamina di tivi dan diakhiri dengan slogan
Kita untung Bangsa untung..
Aku ko jadi mikir. Dan Kayaknya memangnya harus dipikiir dulu.. .sebenarnya siapa sih yang untung?? Pantesnya juga slogannya gi ganti :
Pertamina untung Bangsa buntung.
::ya..begini ini jadi konsumen yang lemah di Idonesia. Mau ngadu, ngadu ke sapa? trus gimana cara ngadunya? klo udah ngadu...lalu apa..? akhirnya cuma bisa gerundel ambe mis*h2 di blog::
itu gambar diatas saya contek dari http://donnaisra.wordpress.com/2006/10/16/gedung-pertamina-yang-ironis/
19 August 2008
gelang
Di hadapan sebuah toko kecil itu tampak Ia kebingungan. Termangu Ia dalam tegaknya. Masih berpikir, haruskah Ia melangkah masuk kedalam, memilih dan memberikan pesan itu untuknya. Ataukah kembali melanjutkan langkahnya. pulang dan kembali melupakannya untuk sejenak, seperti biasanya. Semakin lama ia berdiam di depan toko itu, semakin tampak Ia kebingungan. Bingung. Harus memilih apa dan kapan mesti Ia berikan kepadanya. Jika bukan Ia sendiri yang memberikan mesti lewat siapa harus dititipkan pesan ini.
Sudah lama, bahkan teramat sangat lama, Ia menimbang-nimbang ide ini di kepalanya. Di bolak-balik rencana ini bersama dengan pertanyaan : masih pantaskah? Terlalu anehkah? Norakkah? Dalam rangka apakah? Terus Apa yang nanti akan Ia pikirkan tentang kau?
Pada akhirnya melangkah juga Ia kedalam. Saat masuk dan menyusuri etalase, suara dalam benaknya masih saja datang berkoar “Yang ini norak, yang itu juga”. “Semua yang kau pilih akan tampak norak dihadapannya”. “Ingat, bagaimanapun juga kau harus peduli apa yang Ia pikirkan tentang mu, jadi sudahlah... Jangan kau lanjutkan!”. “Kau terlalu banyak berharap padanya”. “Kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri dihadapannya”.
Ia masih susuri deretan etalase dalam toko itu. Ia melangkah, mendekat, dan memilih apa yang dari sejak dulu Ia rencanakan. Dalam sudut lain dadanya terdengar halus juga suara-suara yang berkelebat: “Ah, apa sih yang norak dari hanya sekedar ngasih perhiasan ke seseorang yang kamu sayangi ?”.
“Emang sampai kapan kau akan tetap tinggal di sini? Jika bukan kau yang pergi sekarang, pasti Ia yang akan pergi. Dan sebelum semuanya pergi, tolong pastikan Ia tak lagi membencimu”. “Sampai kapan kau akan terus berharap pertemuan-pertemuan yang tak terencanakan dengannya”. “Bagaimanapun juga, Ia harus tahu apa yang kau pikirkan tentangnya”.
Akhirnya dipilihnya juga sebuah gelang perak dari deretan paling atas di sebuah etalase yang bening. Sebuah gelang dengan liontin berbentuk hati munggil.
Gelang ini adalah hadiah untuk sekian waktu yang tanpa sempat bersua ia dengannya, apalagi berucap. Untuk hadiah ulang tahun di awal September nanti. Gelang ini untuk cinta yang sederhana. Sederhana dan tak sempurna. Indah dalam pasrahnya untuk tak mencoba jadi sempurna.
Gelang ini untuk seseorang yang dulu pernah ia kenal dalam jenak kehidupannya. Walaupun tak pernah benar-benar ia mengenalnya.
***
Jikalau nanti suatu saat kau lingkarkan untaian ini di pergelangan tangan-mu dan memang terlihat norak, ya ... ini memang sekedar ungkapan rasa yang norak, yang nggak sempurna. Apa adanya.
Sudah lama, bahkan teramat sangat lama, Ia menimbang-nimbang ide ini di kepalanya. Di bolak-balik rencana ini bersama dengan pertanyaan : masih pantaskah? Terlalu anehkah? Norakkah? Dalam rangka apakah? Terus Apa yang nanti akan Ia pikirkan tentang kau?
Pada akhirnya melangkah juga Ia kedalam. Saat masuk dan menyusuri etalase, suara dalam benaknya masih saja datang berkoar “Yang ini norak, yang itu juga”. “Semua yang kau pilih akan tampak norak dihadapannya”. “Ingat, bagaimanapun juga kau harus peduli apa yang Ia pikirkan tentang mu, jadi sudahlah... Jangan kau lanjutkan!”. “Kau terlalu banyak berharap padanya”. “Kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri dihadapannya”.
Ia masih susuri deretan etalase dalam toko itu. Ia melangkah, mendekat, dan memilih apa yang dari sejak dulu Ia rencanakan. Dalam sudut lain dadanya terdengar halus juga suara-suara yang berkelebat: “Ah, apa sih yang norak dari hanya sekedar ngasih perhiasan ke seseorang yang kamu sayangi ?”.
“Emang sampai kapan kau akan tetap tinggal di sini? Jika bukan kau yang pergi sekarang, pasti Ia yang akan pergi. Dan sebelum semuanya pergi, tolong pastikan Ia tak lagi membencimu”. “Sampai kapan kau akan terus berharap pertemuan-pertemuan yang tak terencanakan dengannya”. “Bagaimanapun juga, Ia harus tahu apa yang kau pikirkan tentangnya”.
Akhirnya dipilihnya juga sebuah gelang perak dari deretan paling atas di sebuah etalase yang bening. Sebuah gelang dengan liontin berbentuk hati munggil.
Gelang ini adalah hadiah untuk sekian waktu yang tanpa sempat bersua ia dengannya, apalagi berucap. Untuk hadiah ulang tahun di awal September nanti. Gelang ini untuk cinta yang sederhana. Sederhana dan tak sempurna. Indah dalam pasrahnya untuk tak mencoba jadi sempurna.
Gelang ini untuk seseorang yang dulu pernah ia kenal dalam jenak kehidupannya. Walaupun tak pernah benar-benar ia mengenalnya.
***
Jikalau nanti suatu saat kau lingkarkan untaian ini di pergelangan tangan-mu dan memang terlihat norak, ya ... ini memang sekedar ungkapan rasa yang norak, yang nggak sempurna. Apa adanya.
10 August 2008
Guyonan Kartolo

Saya selalu ikut-ikutan senang bila melihat senyum tawa seorang teman yang mendengarkan acara humor Kartolo lewat radio mp3 nya. Malah sering saya tergoda untuk ikut mendengarkan dagelannya kartolo. Namun anehnya, pas dengerin, saya sering tak bisa tersenyum tawa lucu persis sebagaimana teman saya yang tertawa lucu karena urat gelinya tergelitik.
humornya Kartolo sering kali lolos, tak tertangkap oleh benak saya.
padahal kalo dipikir2 saya sudah cukup mengerti bahasa Jawa, baik mendengar maupun secara verbal, walau pada tingkat tertentu. Tapi toh tetap saja humornya terasa tak begitu lucu-lucu amat. Tetap saja saya sering ga tahu dimana titik lucunya. Tetap saja ga lucu.
perbedaan budaya kah? Ataukah saya yang ga punya akar budaya dengan budaya Jawa? Atau belum benar-benar bisa saya bahasa Jawa?
Saya percaya dan setuju, dalam hal definisi, lucu itu seperti cinta. Ia tak terdefinisikan tapi dapat diekspresikan. Lucu itu abstrak yang universal. (contohnya: kita tahu apa itu lucu, ya.. saat kita ngalamin sensasi lucu. bukan di saat mendengarkan penjelasan apa itu lucu. Bener kan?)
Anehnya, dalam kasus humor Kartolo, ke-universal-an lucu menjadi tidak berlaku. Ke ‘Universal’an lucu itu hilang. Ke-lucu-an itu hanya dapat di rasakan oleh sebagian orang, persisnya orang yang berakar budaya sama dengan Kartolo.
Apakah Humor Kartolo ini humor yang melokal? Bisa jadi iya.
Dan bila iya, hal tersebut menjadi semakin aneh. Aneh karena fenomena tersebut terjadi didunia sekarang ini. Terjadi di zaman ketika tengah gencar dan derasnya pertukaran informasi yang membanjiri (dan mengkontaminasi) tiap-tiap budaya di muka bumi. Dan ditengah hiruk pikuk pertukaran informasi tersebut justru humor Kartolo tetap awet dalam melokal. Ia tidak terkontaminasi. Ia tiddak tergerus oleh humor-humor impor atau humor-humor macam humor Tukul.
Apakah ia awet karena humor Kartolo ini merupakan hal-hal sepele dalam sebuah budaya, cuma sekedar masalah guyonan. Dan justru karena sepele tersebut humor Kartolo menjadi terawetkan dengan sendirinya ?
Atau apa mungkin, justru dalam hal-hal yang seremeh ini masih bisa kita temukan jejaknya 'geist', spirit-nya Heidegger yang membentuk keunikan masing-masing budaya? Bahkan dalam urusan ketawa sekalipun?
Ataukah saya saja yang terlampau bebas menterjemahkan kata ‘universal’ dalam adigium humor itu universal?
Bahwa saya lupa humor itu juga berkaitan dengan intelektual seseorang. Bahwa humor itu juga bisa merupakan kesepakatan tak tertulis antar individu dalam suatu komunitas. Bahwa humor itu juga bisa merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang
Entahlah. Yang pasti dari ketidaktahuan-ketidaktahuan macam itulah hidup jadi lebih kaya untuk dieksplorasi..
Dan karenanya saya jadi lebih semangat untuk belajar lagi budaya dan orang-orang Jawa, yang kata Thedore Friend, membingungkan.
Membingungkan, seperti dalam pengantar bukunya Indonesian Destinies, karena orang Jawa itu ‘menghidupi hidup yang sebagian berupa ungkapan tanpa emosi sementara sebagian lagi berupa emosi yang tak diungkapkan’.
Walaupun ungkapan itu rasanya cocok juga untuk orang-orang Indonesia.
::Nah, itu guyonan Kartolo menurut saya. Banyak tanya dan mengada-ada? Jelas iya, wong saya juga sekedar ngelantur bertutur kok. Yah, kaya ginilah inspirasi yang tertimba dari dengerin humornya Kartolo::
itu gambar saya contek dari frindsternya cak Kartolo http://profiles.friendster.com/user.php?uid=15360112
26 July 2008
Bukuku suka-suka-- mimpi yang minta mewujud
Sampai sekarang saya ini sering iri, yah...iri yang ikhlas, (apa juga ini, iri yang ikhlas??) jika ada seorang teman yang bekerja di bidang per-bukuan atau jurnalistik. Baik ia sekedar tukang desain gambar sampul buku, tukang alih bahasa, tukang cetak, editor, lebih-lebih kalo memang menjadi seorang penulis. (Ketika saya nyatakan perasaan iri itu lha...dikira teman saya itu saya becanda kali ya?. Dia bilang masa iya sih..? Padahal saya serius lho..) Hadirnya perasaan iri tak lebih dari inginnya diri ini ikut berkontribusi (yang walaupun kecil) di bidang per-bukuan, namun tak pernah kesampaian... seperti kata pepatah, iri kan berarti pertanda tak mampu.
Makanya, adanya keinginan kuat untuk ikut berkontribusi di bidang per-bukuan itu, berbulan-bulan yang lalu, saya dan beberapa teman pegiat buku, berkesempatan untuk bereksperimen dengan buku. Kurang lebihnya (akan) ikut menambah referensi buku dengan menerbitkan buku, sumbangsih kecil-kecilan lah ceritanya. Maka terumuskanlah beberapa judul untuk menerbitkan dan mencetak beberapa buku indie... lahirlah proyek dengan tema besar “bukuku suka-suka”. Lha kenapa buku Indie?? Waktu itu (bahkan sampai sekarang) Kita-kita sadar ko, kepala kita ini belum cukup kuat untuk menjebol tebalnya tembok penerbit. Kalo di paksa juga... di khawatirkan bukan temboknya yang retak tapi kepala ini yang ancur...
Bulan-bulan pertama berjalan menyenangkan. Impian-impian besar mulai bermunculan dalam beberapa diskusi kami. Satu dua teman dikontak malah beberapa pengurus KAMMI Malang mau ikut bergabung atau setidaknya memberi janji ikut menulis satu dua artikel dan akan ikut membantu mengadministrasi juga (maklum saja, proyek ini saya masukkan juga ke program kerja di KAMDA..hehe).
Untuk memudahkan dalam pengerjaan, konsep dalam pembuatan buku (sebenarnya) dibuat sederhana. Kami hanya menulis satu-dua artikel dalam satu tema kecil yang sama yang nantinya akan dikumpulkan dan dijadikan satu buku. Jadi bukan karya besar satu orang, tapi berupa kumpulan beberapa tulisan dari beberapa penulis. Bentuk tulisannya pun sengaja dibuat artikel bebas atau esai yang gak seketat karya tulis ilmiah...dan pengerjaan satu temapun dibuat estafet. Jadi kesuksesan sudah membayang dari awal-awal pengerjaan tak terbayang aral rintang yang menghadang.
Namun sayang seribu sayang. (sampai saat ini) Setting waktu (juga tempat?) ternyata belum mengizinkan bagi kami, para (sebagian) mahasiswa pegiat buku, untuk bisa menerbitkan buku tersebut. Yang saya tahu, sayalah yang masih gelagapan menyesuaikan waktu dalam mengerjakan skripsi karena objek penelitiannya di laut sana (di Sukabumi pula). Sempitnya waktulah yang pada akhirnya buku tersebut belum jadi terbit. Alasan klasik, Mungkin.
Sekarang, dihari-hari setelah kembali ke daratan, kerinduan untuk belajar mendefinisikan diri sendiri serta mengenal diri sendiri dan mengenal saudara dan teman lewat bacaan dan tulisan kembali menyeruak ke permukaan diri. Malah menjadi sebuah semangat baru. Namun kali ini, setelah pengalaman buku indie beberapa bulan yang lalu, diri ini jadi harus lebih mengerti akan posisi. Tak bijak rasanya memulai sesuatu dengan skala yang muluk-muluk, apalagi menuntut banyak kepada orang lain. Biarlah impian yang besar ini dimulai dari yang kecil terlebih dahulu. Dari yang pribadi. Biarlah diri ini yang menulis satu-dua artikel dulu tiap bulan dan menempelkannya di media weblog ini. Itupun siapa pula yang mau membacanya. Ah, jangan dulu berpikir siapa yang akan membaca. Mungkin kali ini saat yang tepat untuk sekedar belajar menulis. Syukur-syukur bisa berjalan rutin.
Jadilah sengaja bikin label baru di blog sendiri. Label untuk hal buku-bukuan yang ceritanya akan dibukukan nantinya (semoga). Lahirlah label Bukumorfosis.
Makanya, adanya keinginan kuat untuk ikut berkontribusi di bidang per-bukuan itu, berbulan-bulan yang lalu, saya dan beberapa teman pegiat buku, berkesempatan untuk bereksperimen dengan buku. Kurang lebihnya (akan) ikut menambah referensi buku dengan menerbitkan buku, sumbangsih kecil-kecilan lah ceritanya. Maka terumuskanlah beberapa judul untuk menerbitkan dan mencetak beberapa buku indie... lahirlah proyek dengan tema besar “bukuku suka-suka”. Lha kenapa buku Indie?? Waktu itu (bahkan sampai sekarang) Kita-kita sadar ko, kepala kita ini belum cukup kuat untuk menjebol tebalnya tembok penerbit. Kalo di paksa juga... di khawatirkan bukan temboknya yang retak tapi kepala ini yang ancur...
Bulan-bulan pertama berjalan menyenangkan. Impian-impian besar mulai bermunculan dalam beberapa diskusi kami. Satu dua teman dikontak malah beberapa pengurus KAMMI Malang mau ikut bergabung atau setidaknya memberi janji ikut menulis satu dua artikel dan akan ikut membantu mengadministrasi juga (maklum saja, proyek ini saya masukkan juga ke program kerja di KAMDA..hehe).
Untuk memudahkan dalam pengerjaan, konsep dalam pembuatan buku (sebenarnya) dibuat sederhana. Kami hanya menulis satu-dua artikel dalam satu tema kecil yang sama yang nantinya akan dikumpulkan dan dijadikan satu buku. Jadi bukan karya besar satu orang, tapi berupa kumpulan beberapa tulisan dari beberapa penulis. Bentuk tulisannya pun sengaja dibuat artikel bebas atau esai yang gak seketat karya tulis ilmiah...dan pengerjaan satu temapun dibuat estafet. Jadi kesuksesan sudah membayang dari awal-awal pengerjaan tak terbayang aral rintang yang menghadang.
Namun sayang seribu sayang. (sampai saat ini) Setting waktu (juga tempat?) ternyata belum mengizinkan bagi kami, para (sebagian) mahasiswa pegiat buku, untuk bisa menerbitkan buku tersebut. Yang saya tahu, sayalah yang masih gelagapan menyesuaikan waktu dalam mengerjakan skripsi karena objek penelitiannya di laut sana (di Sukabumi pula). Sempitnya waktulah yang pada akhirnya buku tersebut belum jadi terbit. Alasan klasik, Mungkin.
Sekarang, dihari-hari setelah kembali ke daratan, kerinduan untuk belajar mendefinisikan diri sendiri serta mengenal diri sendiri dan mengenal saudara dan teman lewat bacaan dan tulisan kembali menyeruak ke permukaan diri. Malah menjadi sebuah semangat baru. Namun kali ini, setelah pengalaman buku indie beberapa bulan yang lalu, diri ini jadi harus lebih mengerti akan posisi. Tak bijak rasanya memulai sesuatu dengan skala yang muluk-muluk, apalagi menuntut banyak kepada orang lain. Biarlah impian yang besar ini dimulai dari yang kecil terlebih dahulu. Dari yang pribadi. Biarlah diri ini yang menulis satu-dua artikel dulu tiap bulan dan menempelkannya di media weblog ini. Itupun siapa pula yang mau membacanya. Ah, jangan dulu berpikir siapa yang akan membaca. Mungkin kali ini saat yang tepat untuk sekedar belajar menulis. Syukur-syukur bisa berjalan rutin.
Jadilah sengaja bikin label baru di blog sendiri. Label untuk hal buku-bukuan yang ceritanya akan dibukukan nantinya (semoga). Lahirlah label Bukumorfosis.
22 July 2008
Kalau bisa, Bukan titik akhir
Malam itu entah hari apa dan entah hari ke berapa saya
berada di kapal. Mungkin hari ke lima,
mungkin juga hari ke enam. Ah..entahlah. Sejak hari pertama di kapal, jalannya
waktu memang sudah tak terperhatikan lagi. Tidak terperhatikan, bukan tidak
diperhatikan. Karena memang saya sudah tak sanggup lagi untuk memperhatikan.
Terombang-ambing di Kapal Motor 99 GT di Samudera Hindia
membuat saya seperti terserang penyakit types. Pikiran tak sanggup lagi
konsentrasi lebih dari dua menit. Pikiran mudah melayang kemana-mana. Badan cuma
bisa berbaring karena lemas. Kepala pusing pening seperti digodam. Perut mual
tak bisa makan.
Selama perjalanan sampai saat itu, perut hanya terisi air
teh manis. Tidak lebih. Makanan tak sanggup lewat lebih dari lambung. Saya perhatikan,
jari-jari tangan dan kaki sudah seperti kerangka.
Beginilah kalau orang gunung tersasar berlayar ke samudera:
mabuk laut. Skripsi saya yang membahas pemetaan nelayan longline di Samudera Hindia mengharuskan saya berlayar bersama
nelayan longline ke Samudra Hindia
selama 15 hari.
…
Menjelang tengah malam, para ABK mulai berdatangan ke dek,
tempat dimana ABK beristirahat.
Tampaknya kerja sudah selesai untuk hari itu. Meski masih pusing, saya paksakan
untuk duduk dan ikut dalam percakapan mereka. Percakapan tentang pengalaman
menjadi nelayan. Sebagian dari mereka masih sebaya, beberapa ada yang lebih
muda dari saya. Total ada 12 ABK. Mereka semua dari Pemalang, kota
dekat Cilacap di Jawa Tengah sana.
“Capek, Mas. Kerjanya gak kenal jam. Sehari istirahat paling cuma lima jam, Kadang seharian penuh selesainya pekerjaan. Udah gitu belum tentu dapat ikannya lagi...,” seseorang mengawali pembicaraan.
“Capek, Mas. Kerjanya gak kenal jam. Sehari istirahat paling cuma lima jam, Kadang seharian penuh selesainya pekerjaan. Udah gitu belum tentu dapat ikannya lagi...,” seseorang mengawali pembicaraan.
“Belum kalau ada gelombang besar, Mas,” timpal yang lain.
Seorang teman ABK lain, yang ikut menumpang untuk pulang, ikut bercerita pengalamannya. “Kalau sekarang saya pulang dulu, Mas. Mau ke Bandung. Ada pekerjaan lain. Baru dua bulan setengah saya di laut. Harusnya sih enam bulan,” paparnya, menjelaskan alasan berhenti sementara melaut.
“Lha, terus bayarannya gimana dong?” heran saya.
“Yang penting sudah bisa tutup kasbon, Mas. Delapan ratus ribu sama rokok dua ratus ribu,” ungkapnya.
“Kalo gak melaut kerjanya apa, Mas?” tanyaku.
“Ya...apa saja. Kadang jadi cleaning service di Semarang.”
“Kalo dulu saya ingin melanjutkan sekolah ke SMA, Mas. Tapi orangtua gak punya biaya. Malahan saat pembagian ijazah saya udah melaut.” Seorang lagi anak muda yang dari tadi diam saja, ikut angkat bicara, meski terdengar lebih sebagai gumam ke dirinya sendiri.
“Kalo ada pekerjaan lain, saya mau kerja yang lain, Mas,” ucapnya.
…
Tak persis demikian memang percakapannya, namun semacam itulah. Dan sayapun jadi sadar tentang apa artinya menjadi nelayan bagi (sebagian) anak nelayan. Nelayan adalah pekerjaan yang liat dan pekat dengan resiko. Menjadi nelayan adalah titik berangkat dari hidup mereka, dan bukan titik selesai. Kalau bisa, bukan titik selesai.
Di mata kuliah Ekonomi Perikanan semester dua dulu, tak pernah terbaca dan terpikir bahwa menangkap ikan (menjadi nelayan) adalah sebagai salah satu upaya ekonomis beresiko tinggi. (aduh...maaf..maafff, ini mungkin lebih karena sayanya saja yang jarang baca teks wajib kuliah atau jarang masuk kuliah..). Ternyata saya salah.
Tak persis demikian memang percakapannya, namun semacam itulah. Dan sayapun jadi sadar tentang apa artinya menjadi nelayan bagi (sebagian) anak nelayan. Nelayan adalah pekerjaan yang liat dan pekat dengan resiko. Menjadi nelayan adalah titik berangkat dari hidup mereka, dan bukan titik selesai. Kalau bisa, bukan titik selesai.
Di mata kuliah Ekonomi Perikanan semester dua dulu, tak pernah terbaca dan terpikir bahwa menangkap ikan (menjadi nelayan) adalah sebagai salah satu upaya ekonomis beresiko tinggi. (aduh...maaf..maafff, ini mungkin lebih karena sayanya saja yang jarang baca teks wajib kuliah atau jarang masuk kuliah..). Ternyata saya salah.
Dari awal saat kapal berangkat, perkara BBM (mahal dan
langka), cuaca, hujan, gelombang, arus, angin, umpan, air yang kurang, makanan
yang menipis, dan sebagainya dan sebagainya sudah menghembalang. Ketika ikan di
tanganpun masalah tak terhenti, hanya berganti nama menjadi pembusukkan,
panjangnya rantai distribusi, penyimpanan, harga rendah, dan lainsebagainya-dan
lainsebagainya.
Menjadi nelayan memang bukan tentang melulu menaklukkan lautan tapi lebih menaklukkan diri sendiri. Ia menuntut keberanian, kesabaran, keuletan, dan pada akhirnya kepasrahan. Walaupun banyak yang tak setuju premis tersebut, pada akhirnya kita mesti menerima bahwa seperti itulah kenyataan nelayan kita saat ini.
Di luar, gelombang masih mengguncang lambung kapal. Gelap semakin pekat. Angin kencang dengan aroma garam masih menusuk hidungku. Saya berbaring limbung.
Menjadi nelayan memang bukan tentang melulu menaklukkan lautan tapi lebih menaklukkan diri sendiri. Ia menuntut keberanian, kesabaran, keuletan, dan pada akhirnya kepasrahan. Walaupun banyak yang tak setuju premis tersebut, pada akhirnya kita mesti menerima bahwa seperti itulah kenyataan nelayan kita saat ini.
Di luar, gelombang masih mengguncang lambung kapal. Gelap semakin pekat. Angin kencang dengan aroma garam masih menusuk hidungku. Saya berbaring limbung.
05 July 2008
Perihal buku
Banyak karya tulis atau buku yang kontroversi bermunculan di bumi ini. Dari dulu sampai sekarang (dan sepertinya terus pada yang akan datang). Mulai dari buku yang isinya hanya kutipan ucapan seseorang. catatan harian yang tanpa maksud diterbitkan. beberapa bait puisi. Cerita atau novel dari yang tipis sampai berjilid-jilid. Buku yang isinya sebuah hasil pemikiran mendalam tentang satu hal, sampai dengan tafsir dari sebuah kitab suci. Semua bisa menjadi obyek kontroversi dan karenanya para penulisnya siap dihujat dan bukunya terancam musnah.
Buku memang salah satu subyek subversi paling tua di dunia manusia modern. Dan karenanya tak akan habis kita contoh dari sebuah karya tulis (teks) yang mampu menjadikan penulisnya dihukum bahkan sampai mati dan kemudian teksnya di haramkan beredar. Banyak contoh betapa teks/buku bisa dirasakan sedemikian mengancam (dan merugikan) keadaan dan keberadaan suatu pihak sehingga pihak yang merasa dirugikan merasa perlu mencitrakan buku tersebut sebagai obyek yang berbaya bagi kepentingan umum dan karena itu melarang keberadaannya.
Dan dari semua itu yang membuat saya benar-benar gak suka (bahkan benci) adalah banyak mereka yang buka mulut tentang obyek teks yang menjadi kontroversi tanpa pernah membaca karya tersebut. Atau lebih jauh lagi, adalah betapa mudahnya manusia membebek, betapa mudahnya manusia menelan habis hasil pencitraan suatu pihak yang merasa dirugikan oleh buku tersebut, dan atau membiarkan prasangka pribadi menjadi sebuah citraan yang riil, tanpa pernah sedikitpun atau keinginan untuk memegang buku yang menjadi kontroversi ditangan sendiri, membacanya dengan mata kepala sendiri, lalu menimbang benar buku tersebut buat diri sendiri. Banyak yang percaya begitu saja bahwa buku itu isinya jelek/berbaya/ hanya semata-mata orang lain bilang itu jelek, berbahaya, atau teori kafir.
Kenapa ini perlu? karena sepanjang perjalanan saya, saya melihat kita cenderung acuh dan menutup mata bahkan jadi anti diskusi tentang objek kontroversi. Dan kebiasaan seperti ini saya pikir berbahaya dan juga bodoh. Berbahaya karena dengan acuh dan menutup mata, kita menjadi tidak berpikir kritis terhadap asumsi agama atau idealisme yang kita percaya. Berbahaya karena tanpa pemikiran kritis atau diskusi terbuka sebenarnya proses pemicikan dan pengkerdilan manusia sedang berlangsung. Jadinya banyak orang yang kemudian hanya melihat satu sisi saja.
***
Saya punya sedikit pengalaman (sedikit ? karena jika dibandingkan dengan jumlah teks kontroversi yang ada bacaan saya belum ada apa-apanya) berkenaan dengan buku-buku yang “pernah” menjadi kontroversi dan sempat dilarang per-edarannya. Bagi saya, adalah studi menarik mengetahui isi kenapa sebuah teks menjadi kontroversi apalagi mengikuti perdebatan pro dan kontra diantara keduanya. Karena saya lebih tertarik di bidang sastra bacaannyapun tak lebih berputar disekitar itu saja. Seperti Pledoi Sastra “Langit Makin Mendung” Kipanjikusmin, Pergolakan pemikiran Isam : Catatan Harian Ahmad Wahib, benar-benar menyenangkan bisa berdialog bersimpang pendapat dengan pikiran seseorang yang berani menantang institusi sekelas agama.
Buku Ahmad Tohari dengan Trilogi Dukuh Paruk toh ternyata sedap untuk dibaca, mengikuti kisah lenggak-lenggok hidup Srintil dalam mencari sejatinya kehidupan. Pram dengan kuartet pulau buru : Bumi Manusia, Anak Segala Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca yang jadi favoritku pernah jg sempat dilarang. Baca buku tersebut saya seperti dimasukkan ketempat dan masa dimana setting cerita berlangsung. Abis baca pun saya jadi bertanya penguasa macam apa yang melarang buku yang mengandung nilai sejarah macam tersebut.
Dekontruksi kebenaran sebenarnya bukan teks asli tapi cukuplah untuk awalan untuk membaca teks-teks kontroversi barat macam marx, freud dan lain-lainya. Max Havelar nya Multatuli saya pikir pada masanya sangat kontroversi sekali dan lebih karena itu, MUltatuli mampu memasukkan (kaidah) puisi-puisi romantik dalam cerita yang dasarnya sebuah gugatan terhadap kerajaan Belanda waktu itu. Dan rasanya gak lengkap jika ga nyertain Petunjuk Jalan-nya Sayyid Qutbh, Ini buku menurutku inspiratif banget, (Walaupun sampai sekarang belum tamat-tamat saya bacanya). Apalagi klo ngelihat akibat yang ditimbulkan dari buku ini. Mulai dari penulisnya sampai yang membacanya..
****
Lha, ko Cuma sedikit?? Mana Marx, Darwin, Mein Kramp (ejaannya bener g y?)... hehehe itu aza dulu ya. Kalo udah baca entar saya komentar...
Kalo Dan Brown sama Jk Rowling mah menurutku biasa-biasa saja. Maksudnya ga harus masukkin daftar buku kontroversi gitu, walaupun sebagian orang tidak bersetuju dengan buku2 tersebut.
::
Kenapa saya ngomongin buku dan bukan karya yang lain :Karena saya (merasa) lebih banyak bersentuhan dengan buku (teks) dibandingkan dengan karya musik, gambar, atau bahkan teater. Dan karna itu saya jadi lebih PeDe aza ketika ngomonginnya. walaupun Pede toh omongannya belum tentu benar. Bener ga sih ??
::
01 July 2008
Kebebasan adalah ilusi, benarkah ??
Begitu kata maul (dan mungkin kata sebagian orang ?).
Tapi benarkah ??
Bahwa kebebasan, keinginan untuk bebas, adalah ilusi,
dan karenanya tidak benar ada kecuali hanya dalam khayal manusia saja. Makanya tak boleh hadir kecuali hanya di rongga kepala manusia.
Tapi benarkah juga ( yang kata sebagian orang juga ??),
dengan bilang bahwa keinginan bebas adalah satu-satunya modal yang berlaku di dunia. Bahwa manusia tanpa keinginan bebas bukanlah manusia ??
Premis pertama di atas jika ditelusuri dengan seksama, akan sampai pada sebuah “kesadaran” bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah tanggung jawab Allah semata, makanya, bahwa Allah dan hanya Allah sajalah yang mesti dipersalahkan dan dibenarkan atas semua pilihan (tentu saja dengan akibat pada pilihan tersebut) semua ciptaanNya.
Sedangkan dari premis kedua mengisyaratkan bahwa Allah hanya menonton saja pentas kehidupan dari ciptaanNya dan berpangku tangan atas semua adegan dan peran kehidupan yang berlangsung di pentas kehidupan tersebut. Allah yang meski kuasa namun tak ingin bercampur tangan.
Masyarakat seperti ini ingin Tuhan. tapi risi dengan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Melihat ciptaanNya dimana dan kapanpun. Risi dengan Tuhan yang terus mengikutinya. Ia ingin Allah yang voyeuris.
Tuhan yang seperti seorang ayah yang sudah mati. Sosoknya lebih dirindukan dan dihormati (dibanding saat hidup) oleh anaknya, karena sang ayah tidak ikut campur terhadap kehidupan anaknya.
Bukankah pada akhirnya dua-duanya sama tidak bijaksananya ?? Bukankah keduanya tak lebih dari dua kutub ekstrim dari satu magnet ? bukankah keduanya hanya titik puncak sebuah frekuensi? bukankah dua-duanya tak mewakili sejatinya kebenaran ?
Entahlah, kalau menurut sampeyan gimana ?
Paling enak bikin tulisan seperti diatas. Ga tanggung jawab Membiarkannya menggantung.
::Ah..dasar sok tahu dan tidak bertanggung jawab !::
Tapi benarkah ??
Bahwa kebebasan, keinginan untuk bebas, adalah ilusi,
dan karenanya tidak benar ada kecuali hanya dalam khayal manusia saja. Makanya tak boleh hadir kecuali hanya di rongga kepala manusia.
Tapi benarkah juga ( yang kata sebagian orang juga ??),
dengan bilang bahwa keinginan bebas adalah satu-satunya modal yang berlaku di dunia. Bahwa manusia tanpa keinginan bebas bukanlah manusia ??
Premis pertama di atas jika ditelusuri dengan seksama, akan sampai pada sebuah “kesadaran” bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah tanggung jawab Allah semata, makanya, bahwa Allah dan hanya Allah sajalah yang mesti dipersalahkan dan dibenarkan atas semua pilihan (tentu saja dengan akibat pada pilihan tersebut) semua ciptaanNya.
Sedangkan dari premis kedua mengisyaratkan bahwa Allah hanya menonton saja pentas kehidupan dari ciptaanNya dan berpangku tangan atas semua adegan dan peran kehidupan yang berlangsung di pentas kehidupan tersebut. Allah yang meski kuasa namun tak ingin bercampur tangan.
Masyarakat seperti ini ingin Tuhan. tapi risi dengan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Melihat ciptaanNya dimana dan kapanpun. Risi dengan Tuhan yang terus mengikutinya. Ia ingin Allah yang voyeuris.
Tuhan yang seperti seorang ayah yang sudah mati. Sosoknya lebih dirindukan dan dihormati (dibanding saat hidup) oleh anaknya, karena sang ayah tidak ikut campur terhadap kehidupan anaknya.
Bukankah pada akhirnya dua-duanya sama tidak bijaksananya ?? Bukankah keduanya tak lebih dari dua kutub ekstrim dari satu magnet ? bukankah keduanya hanya titik puncak sebuah frekuensi? bukankah dua-duanya tak mewakili sejatinya kebenaran ?
Entahlah, kalau menurut sampeyan gimana ?
Paling enak bikin tulisan seperti diatas. Ga tanggung jawab Membiarkannya menggantung.
::Ah..dasar sok tahu dan tidak bertanggung jawab !::
Tak akan lagikah
Tak Akan lagikah??
Sadarku kini tak selalu ada di benakku
Sadarku tentang hadirMU
Sadarku akan MahaMu
Sudah terbaring lama aku berpeluh
Penuh Dosa
Perih penuh luka
Terpanggang laku sendiri
Tak terdengar lagi segala perintahMu
Yang biasa berdesir di semua nadiku
Tak terdengar lagi bisikMU
Yang biasa bergetar di hatiku
Tak kurasa lagi kehadiranMu
Di debar jantungku
Tak akan lagikah??
Tak akan lagikah?
Aku yang memanggilMU?
Atau sebaliknya, Kau yang Menyapaku?
Kucari Kau ditempat biasa kumenemuiMu
Dalam sujudku
Dalam renungku
Dalam diamku
Dalam seluruhku
Tak akan lagikah Kau hadir,
Mampir di lelap tidurku ?
Bercakap dalam senyap diantara lelap?
Ah,
Mungkin kini sudah Tak tahu aku
bagaimana adab bercakap denganMu ?
Sukabumi
Satu Juli 08
Sadarku kini tak selalu ada di benakku
Sadarku tentang hadirMU
Sadarku akan MahaMu
Sudah terbaring lama aku berpeluh
Penuh Dosa
Perih penuh luka
Terpanggang laku sendiri
Tak terdengar lagi segala perintahMu
Yang biasa berdesir di semua nadiku
Tak terdengar lagi bisikMU
Yang biasa bergetar di hatiku
Tak kurasa lagi kehadiranMu
Di debar jantungku
Tak akan lagikah??
Tak akan lagikah?
Aku yang memanggilMU?
Atau sebaliknya, Kau yang Menyapaku?
Kucari Kau ditempat biasa kumenemuiMu
Dalam sujudku
Dalam renungku
Dalam diamku
Dalam seluruhku
Tak akan lagikah Kau hadir,
Mampir di lelap tidurku ?
Bercakap dalam senyap diantara lelap?
Ah,
Mungkin kini sudah Tak tahu aku
bagaimana adab bercakap denganMu ?
Sukabumi
Satu Juli 08
14 June 2008
tak pernah sampai
Lidahku bisa setajam belati
Seharum wangi melati
Seindah warna pelangi
Bisa menari seelok burung kenari
Yang merampas banyak hati
namun
Dihadapanmu lidahku mati
Aksara
Kata
Makna
Mantra
Tak sampai-sampai
Kepadamu
Menggapai-gapai
Tapi tak pernah sampai kepadamu
Tak pernah sampai
Seharum wangi melati
Seindah warna pelangi
Bisa menari seelok burung kenari
Yang merampas banyak hati
namun
Dihadapanmu lidahku mati
Aksara
Kata
Makna
Mantra
Tak sampai-sampai
Kepadamu
Menggapai-gapai
Tapi tak pernah sampai kepadamu
Tak pernah sampai
24 May 2008
ada reformasi di Indonesia
Ada reformasi di Indonesia. Di bulan Mei 1998 -waktu itu- ada gelombang massa yang mendesak-desak menghancurkan, mencoba mematahkan sebuah kekuasaan yang memaksakan untuk tegak walau sudah renta dan retak. Ada massa yang besar yang menggugat kekuasaan, tapi ini bukan revolusi walaupun -pada akhirnya- ada kekuasaan yang tumbang.
Di bulan Mei, 10 tahun yang lalu, ketika hidup rakyat sudah lama terhimpit-himpit. Saat harga membumbung tinggi, dan perbedaan sudah lama menjadi sebuah kejahatan atas nama kestabilan dan keselarasan. Ketika tanah rakyat dicaplok dan aktifis ditahan atas nama pembangunan. Ribuan orang akhirnya harus turun kejalan, yang tidak hanya di ibu kota Jakarta, mencoba merubah takdir negeri ini : REFORMASI
Reformasi mulai di dengung-dengungkan, diteriakkan, dan akhirnya dikumandangkan dimana-mana. Reformasi berubah seperti menjadi mantra. mantra untuk kehidupan dan keselamatan. Di jalan-jalan oleh mahasiswa dirapalkan, di gedung dewan dibahas dan diusulkan, di istana Negara dititahkan, para pengamat mendiskusikan. Semua mengusung reformasi dan mengaku paling reformis. Seolah jika tidak menggunakan mantra ini, orang akan hilang ditelan zaman tanpa seorangpun akan mengingatnya di masa depan.
Namun pada waktu itu siapa yang paling reformis? Siapa!? Siapa makan siapa!?
Jalan sejarah memang tak selalu datar dan lurus, walau tak selamanya berkelok dan menurun tajam. Ditikungan sejarah itu reformasi muncul dan mulai menemukan salah satu tujuannya. Getarnya dahsyat, namun seperti disetiap perjuangan selalu ada pengorbanan dan selalu ada yang mau berkorban walau banyak yang menjadi korban. Empat mahasiswa harus tertembus peluru dahulu sebelum Soeharto mundur.
Saat itu “reformasi” adalah sebuah cita-cita untuk kehidupan masa depan. Reformasi adalah sebuah perlambang untuk optimisme, janji dan harapan akan masa datang yang lebih baik. Namun ketika janji dan harapan reformasi –sampai sekarang- tidak kunjung mewujud, sekarang “reformasi” seperti hanya menjadi bagian dari sejarah yang terikat dalam ruang masa lalu. Ia tertinggal menunggu lupa dan dibuang, atau ingat dan diperjuangkan kembali.
Reformasi ternyata bukan sebuah lorong lurus yang bisa mengikuti setiap zaman. Banyak bagiannya tak lagi utuh karena tak bisa melewati waktu atau memang sengaja tidak dilewatkan. ia harus diingat, meski ada yang jeri dalam nostalgia. karena kita sadar reformasi bukan mantra yang kesaktiannya melekat pada kata disepanjang abad.
Setelah sepuluh tahun reformasi. Saat sepuluh tahun reformasi mulai diperingati... ketika harapan dan cita-cita untuk mendapatkan keadilan dan mensejahterakan rakyat dari pahlawan reformasi tak kunjung terwujud. Saat cita-cita hanya tingal menjadi cita-cita. Kita dikagetkan oleh kenyataan bahwa kehidupan memang tak kunjung lebih baik dibanding di urus oleh pak Harto sendirian. Kita dihenyakkan oleh keadaan banhwa ternyata banyak kualitas aspek kehidupan tak jua kunjung membaik. Ternyata kita belum benar-benar becus mengurus negara dibanding di bawah titah pak Harto.
seseorang pernah bertanya:
lantas apakah kehidupan menjadi lebih baik setelah negeri ini di tinggalkan oleh Soeharto?
Lalu buat apa reformasi?
Entah...
mungkin Reformasi memang hanya menjadi sebuah lambang optimisme dan harapan yang jawabannya seperti sebuah anekdot nama bulan dimana reformasi ini menemukan puncaknya.
Mei be yes mei be no.
Entahlah..
Tapi yang jelas setelah Soeharto lengser bahwa kini “kita”-lah yang mengurus dan menetukan arah negeri ini dan bukan hanya dari telunjuk seseorang. Bahwa kini kita belajar menerima yang lain yang berbeda dalam ruang demokrasi. Mungkin itulah sebagian makna dari reformasi. Bahwa tak ada yang bisa disalahkan, kecuali “kita” sendiri. Mungkin itulah sebagian hasil dari reformasi dahulu, kita bebas menentukan arah bangsa ini bebas berbeda walau ternyata tak cukup makan dan tak cukup energi.
:: hanya untuk ingat dan mencari akar dengan menengok masa lampau.Karena orientasi melihat masa depan akan kurang lengkap jika orientasi ke masa lampau tidak ada* ::
*dikutip dan dimodifikasi dari tulisannya budi darma yang berjudul menengok masa lampau. Dari buku Kumpulan Cerpen Budi Darma Fofo dan Senggring.
Di bulan Mei, 10 tahun yang lalu, ketika hidup rakyat sudah lama terhimpit-himpit. Saat harga membumbung tinggi, dan perbedaan sudah lama menjadi sebuah kejahatan atas nama kestabilan dan keselarasan. Ketika tanah rakyat dicaplok dan aktifis ditahan atas nama pembangunan. Ribuan orang akhirnya harus turun kejalan, yang tidak hanya di ibu kota Jakarta, mencoba merubah takdir negeri ini : REFORMASI
Reformasi mulai di dengung-dengungkan, diteriakkan, dan akhirnya dikumandangkan dimana-mana. Reformasi berubah seperti menjadi mantra. mantra untuk kehidupan dan keselamatan. Di jalan-jalan oleh mahasiswa dirapalkan, di gedung dewan dibahas dan diusulkan, di istana Negara dititahkan, para pengamat mendiskusikan. Semua mengusung reformasi dan mengaku paling reformis. Seolah jika tidak menggunakan mantra ini, orang akan hilang ditelan zaman tanpa seorangpun akan mengingatnya di masa depan.
Namun pada waktu itu siapa yang paling reformis? Siapa!? Siapa makan siapa!?
Jalan sejarah memang tak selalu datar dan lurus, walau tak selamanya berkelok dan menurun tajam. Ditikungan sejarah itu reformasi muncul dan mulai menemukan salah satu tujuannya. Getarnya dahsyat, namun seperti disetiap perjuangan selalu ada pengorbanan dan selalu ada yang mau berkorban walau banyak yang menjadi korban. Empat mahasiswa harus tertembus peluru dahulu sebelum Soeharto mundur.
Saat itu “reformasi” adalah sebuah cita-cita untuk kehidupan masa depan. Reformasi adalah sebuah perlambang untuk optimisme, janji dan harapan akan masa datang yang lebih baik. Namun ketika janji dan harapan reformasi –sampai sekarang- tidak kunjung mewujud, sekarang “reformasi” seperti hanya menjadi bagian dari sejarah yang terikat dalam ruang masa lalu. Ia tertinggal menunggu lupa dan dibuang, atau ingat dan diperjuangkan kembali.
Reformasi ternyata bukan sebuah lorong lurus yang bisa mengikuti setiap zaman. Banyak bagiannya tak lagi utuh karena tak bisa melewati waktu atau memang sengaja tidak dilewatkan. ia harus diingat, meski ada yang jeri dalam nostalgia. karena kita sadar reformasi bukan mantra yang kesaktiannya melekat pada kata disepanjang abad.
Setelah sepuluh tahun reformasi. Saat sepuluh tahun reformasi mulai diperingati... ketika harapan dan cita-cita untuk mendapatkan keadilan dan mensejahterakan rakyat dari pahlawan reformasi tak kunjung terwujud. Saat cita-cita hanya tingal menjadi cita-cita. Kita dikagetkan oleh kenyataan bahwa kehidupan memang tak kunjung lebih baik dibanding di urus oleh pak Harto sendirian. Kita dihenyakkan oleh keadaan banhwa ternyata banyak kualitas aspek kehidupan tak jua kunjung membaik. Ternyata kita belum benar-benar becus mengurus negara dibanding di bawah titah pak Harto.
seseorang pernah bertanya:
lantas apakah kehidupan menjadi lebih baik setelah negeri ini di tinggalkan oleh Soeharto?
Lalu buat apa reformasi?
Entah...
mungkin Reformasi memang hanya menjadi sebuah lambang optimisme dan harapan yang jawabannya seperti sebuah anekdot nama bulan dimana reformasi ini menemukan puncaknya.
Mei be yes mei be no.
Entahlah..
Tapi yang jelas setelah Soeharto lengser bahwa kini “kita”-lah yang mengurus dan menetukan arah negeri ini dan bukan hanya dari telunjuk seseorang. Bahwa kini kita belajar menerima yang lain yang berbeda dalam ruang demokrasi. Mungkin itulah sebagian makna dari reformasi. Bahwa tak ada yang bisa disalahkan, kecuali “kita” sendiri. Mungkin itulah sebagian hasil dari reformasi dahulu, kita bebas menentukan arah bangsa ini bebas berbeda walau ternyata tak cukup makan dan tak cukup energi.
:: hanya untuk ingat dan mencari akar dengan menengok masa lampau.Karena orientasi melihat masa depan akan kurang lengkap jika orientasi ke masa lampau tidak ada* ::
*dikutip dan dimodifikasi dari tulisannya budi darma yang berjudul menengok masa lampau. Dari buku Kumpulan Cerpen Budi Darma Fofo dan Senggring.
11 April 2008
setia
adakah kau dengar lagu merdu
di kerlap-kerlip cahaya kunang-kunang,
pada cakrawala
pada cahaya
pernahkah kau dengar musik indah
di jatuhnya helai daun
yang menguning
terbawa angin,
pada gelap
pada lelap
adakah kau dengar irama sendu
saat kau lihat rintik gerimis di senjakala
atau titik hujan yang menumbuk telaga,
pada curahan air mata yang tak tertahan
walau tak ada aku bersamamu
tapi bila kau dengar semua itu
mengertilah kau
bahwa aku selalu ada bersamamu
dalam tiap serat keberadaanku
di kerlap-kerlip cahaya kunang-kunang,
pada cakrawala
pada cahaya
pernahkah kau dengar musik indah
di jatuhnya helai daun
yang menguning
terbawa angin,
pada gelap
pada lelap
adakah kau dengar irama sendu
saat kau lihat rintik gerimis di senjakala
atau titik hujan yang menumbuk telaga,
pada curahan air mata yang tak tertahan
walau tak ada aku bersamamu
tapi bila kau dengar semua itu
mengertilah kau
bahwa aku selalu ada bersamamu
dalam tiap serat keberadaanku
30 March 2008
kokok ayam dan secangkir kopi

Fajar menyemburat memulas langit. Pagi baru tlah datang dimulai jauh dari horizon timur sana. Awal hari datang menyapa. Aktivitas pagi di sini, di rumah, di Sukabumi, benar-benar terasa berbeda dilalui. Di sisni, aktivitas pagi harus dilewati lebih awal, sesaat sebelum matari menampakkan sinarnya. Dan di hari-hari seperti ini, baru tersadar ada hal baru yang teraba saat menjalani ritual pagi di rumah: ada kokok ayam jantan dan ada secangkir kopi panas menemani aktifitas pagi.
Malang sebenarnya ga metropolitan2 banget. Ga kota-kota amat. Tapi hidup di antara himpitan rumah dengan rumah, berjajar dalam sebuah gang sempit, mendengarkan suara kokok ayam jantan penanda pagi atau cicit burung di awal hari menjadi sebuah kesempatan yang langka. Sebenarnya, disamping rumah kontrakan di Malang ada keluarga yang memelihara ayam, Sepasang atau dua pasang ayam, namun entah kenapa, kokok ayam jantannya selalu lolos tak tertangkap oleh telinga di pagi hari. Selepas sholat subuh kokok ayam jantan sering tak terjaring oleh telinga atau mungkin memang tak saya sadari.
Di rumah, sesaat sebelum fajar muncul, kokok ayam jantan terdengar bersahutan berpadu membahana. Dimulai sejak awal kumandang adzan subuh sampai matahari cukup silau jika di pandang.
Dan secangkir kopi....
Emang dulu saya sempat keranjingan (bahkan mungkin ketagihan) menegak minuman berkafein rendah macam kopi neskape. tapi kebiasaan itu berangsur hilang bersamaan dengan mulai banyaknya pengetahuan yang terserap tentang bahaya kafein bagi tubuh. Mengkonsumsi kopi di Malang, saya lakukan paling cuma sekedar untuk menemani ketika baca koran hari Minggu, yang tidak bisa saya santap pagi-pagi, yang baru bisa saya dinikmati malamnya di warung “kayungyun”. Atau saat pusing bergulung di kepala, kopi berat menjadi pereda gejala tersebut sebelum beralih keobat-obat warung macam bodrex.
Sedangkan di rumah, kopi tanpa disadari menjadi teman aktvitas hampir disetiap pagi harinya. Uapnya yang mengapung pelan cukup memanaskan pagi yang dingin dan menahan kantuk yang kadang kambuh sehabis subuh. Dan yang pasti minum kopi di rumah tidak perlu mengupas biaya pengeluaran seperti.
Kokok ayam jantan dan secangkir kopi...
Perbedaan-perbedaan kecil macam itu yang mungkin selalu menyenangkan saat dirumah. Hal yang tak mungkin dirasakan di tempat lain. Walaupun ada pasti ada yang berbeda. Hal yang sepele namun biasanya terpatri abadi dan menjadi sesuatu yang dirindukan saat berada jauh.
Sukabumi.
26 March 2008
hujan
Hujan.
Kau selalu tak percaya, Q, memperhatikan hujan turun dari balik jendela kamar atau berjalan ditengah guyuran air hujan adalah sebuah keindahan. Ah, Q sayang, kau tak pernah percaya. Seberapa sering kukatakan sebanyak itu pula kau tak percaya. Dan semakin kau tak percaya, Q, semakin ingin aku bercerita tentang keindahan hujan dan meyakinkanmu tentang keajaibannya.
Tapi untuk kali ini cobalah dengar sekali lagi ceritaku tentang hujan, Q. Kau pasti sudah mendengar cerita ini kan, Q. Namun dengarkanlah sekali lagi, Q, mungkin ini ceritaku yang terakhir kali. Cerita tentang hujan. Hujan kita, Q.
Ditengah guyuran hujan yang deras, jika tak kubawa sesutu yang penting, yang akan rusak jika basah, kadang aku sengaja berjalan, Q. Dan kurasakan tetesan hujan itu, berat dan menghujam di kulitku. Ia turun dengan bebas, tegak menghantam bumi lalu bergabung dengan tetesan lain mengalir entah kemana, Ke sungai mungkin juga sampai ke laut. Air hujan itu turun serempak berderap seperti regu baris berbaris, teratur, namun sekali lagi kukatan, ia bebas, Q.
Aku sering bertanya dalam hati, Q, ada berapa tetesan air yang turun dari atas sana. Jutaan, bukan, dari tak terhitung turun dan menjadi tak terhingga. Q, entah kenapa aku masih ingat tatkala terjebak atau sengaja berjalan diderasnya hujan. Entah kenapa juga aku pasti ingat dimana saja dan kapan aku berada ditengah hujan itu, Q. Kenangan terguyur hujan pasti menempel erat di pikiranku, ia tak mengelupas dimakan waktu.
Pernah suatu kali juga aku terjebak derasnya hujan di atas motor, Q. Air hujan berubah menjadi tajam, ia menyakitkan, Q. Ia seperti mengiris kulitku. Tajam. Berat. Payung? Jas Hujan? Ah, aku sering tak memakainya, Q. Aku lebih senang rambutku basah dan wajahku terkena tetes demi tetes air hujan itu. Menyenangkan. Ia keras ketika menimpa wajahku namun juga seketika menjadi lembut, Mengalir diwajahku. Ia dingin dan membuat segalanya menjadi basah dan hidup. Hidup? Ya Hidup!
Q, Pernah kutengadahkan wajahku ke langit melihat datangnya hujan. Yang kulihat hanya awan, Q. Awan yang kelabu, terkadang hitam menggantung, menggelayut di langit, berat tak tertahankan. Dan aku senang melihatnya, Q. Ingat, suatu saat Kau harus melepaskan bebanmu semuanya, Q, bebas. Seperti awan itu. Ia mengeluarkan semua beban itu sampai ia cukup ringan terbawa angin. Lalu pergi.
Q, masih ingat kau cerita tentang gerimis. Hujan yang rintik itu, Q. Hujan yang turunnya terus menerus namun pelan dan berat. pelan, jarang dan seakan penuh harap. Sering kukatakan gerimis itu hujan yang sedih, Q. Hujan yang menangis. Karena ada harap yang tak terpenuhi. Gerimis adalan hujan antara deras yang kuat dan mendung yang lemah. Ia hujan yang tak sempurna, namun ia indah, Q. Ia adalah sedih yang pasrah. Karena itu ia menjadi indah. Indah dalam pasrahnya untuk menjadi tak sempurna. Sebab itu gerimis selalu merampas hati. Ia datang mendesak kedalam hati ku, Q .
Pernah suatu malam kau bersikeras ingin menggandengku, bersama berjalan dalam lindungan payung mu Q, Namun aku menolak. Ah, kau mungkin sudah lupa, Q. Waktu itu Kau mencemaskanku yang akan sakit bila terguyur hujan. Nggak, Q. Nggak! Hujan adalah temanku, seperti kau juga temanku, Q. Teman tak mungkin menyakiti sahabatnya sendiri. Iya kan, Q.
Aku merindukanmu Q. Hujan yang akan segera berakhir menjelang kemarau ini membuatku sedih. Aku rindu hujan, hujan kita Q.
Dari teman imajiner.
Sukabumi,
Kala musim hujan
Kan berganti
Kau selalu tak percaya, Q, memperhatikan hujan turun dari balik jendela kamar atau berjalan ditengah guyuran air hujan adalah sebuah keindahan. Ah, Q sayang, kau tak pernah percaya. Seberapa sering kukatakan sebanyak itu pula kau tak percaya. Dan semakin kau tak percaya, Q, semakin ingin aku bercerita tentang keindahan hujan dan meyakinkanmu tentang keajaibannya.
Tapi untuk kali ini cobalah dengar sekali lagi ceritaku tentang hujan, Q. Kau pasti sudah mendengar cerita ini kan, Q. Namun dengarkanlah sekali lagi, Q, mungkin ini ceritaku yang terakhir kali. Cerita tentang hujan. Hujan kita, Q.
Ditengah guyuran hujan yang deras, jika tak kubawa sesutu yang penting, yang akan rusak jika basah, kadang aku sengaja berjalan, Q. Dan kurasakan tetesan hujan itu, berat dan menghujam di kulitku. Ia turun dengan bebas, tegak menghantam bumi lalu bergabung dengan tetesan lain mengalir entah kemana, Ke sungai mungkin juga sampai ke laut. Air hujan itu turun serempak berderap seperti regu baris berbaris, teratur, namun sekali lagi kukatan, ia bebas, Q.
Aku sering bertanya dalam hati, Q, ada berapa tetesan air yang turun dari atas sana. Jutaan, bukan, dari tak terhitung turun dan menjadi tak terhingga. Q, entah kenapa aku masih ingat tatkala terjebak atau sengaja berjalan diderasnya hujan. Entah kenapa juga aku pasti ingat dimana saja dan kapan aku berada ditengah hujan itu, Q. Kenangan terguyur hujan pasti menempel erat di pikiranku, ia tak mengelupas dimakan waktu.
Pernah suatu kali juga aku terjebak derasnya hujan di atas motor, Q. Air hujan berubah menjadi tajam, ia menyakitkan, Q. Ia seperti mengiris kulitku. Tajam. Berat. Payung? Jas Hujan? Ah, aku sering tak memakainya, Q. Aku lebih senang rambutku basah dan wajahku terkena tetes demi tetes air hujan itu. Menyenangkan. Ia keras ketika menimpa wajahku namun juga seketika menjadi lembut, Mengalir diwajahku. Ia dingin dan membuat segalanya menjadi basah dan hidup. Hidup? Ya Hidup!
Q, Pernah kutengadahkan wajahku ke langit melihat datangnya hujan. Yang kulihat hanya awan, Q. Awan yang kelabu, terkadang hitam menggantung, menggelayut di langit, berat tak tertahankan. Dan aku senang melihatnya, Q. Ingat, suatu saat Kau harus melepaskan bebanmu semuanya, Q, bebas. Seperti awan itu. Ia mengeluarkan semua beban itu sampai ia cukup ringan terbawa angin. Lalu pergi.
Q, masih ingat kau cerita tentang gerimis. Hujan yang rintik itu, Q. Hujan yang turunnya terus menerus namun pelan dan berat. pelan, jarang dan seakan penuh harap. Sering kukatakan gerimis itu hujan yang sedih, Q. Hujan yang menangis. Karena ada harap yang tak terpenuhi. Gerimis adalan hujan antara deras yang kuat dan mendung yang lemah. Ia hujan yang tak sempurna, namun ia indah, Q. Ia adalah sedih yang pasrah. Karena itu ia menjadi indah. Indah dalam pasrahnya untuk menjadi tak sempurna. Sebab itu gerimis selalu merampas hati. Ia datang mendesak kedalam hati ku, Q .
Pernah suatu malam kau bersikeras ingin menggandengku, bersama berjalan dalam lindungan payung mu Q, Namun aku menolak. Ah, kau mungkin sudah lupa, Q. Waktu itu Kau mencemaskanku yang akan sakit bila terguyur hujan. Nggak, Q. Nggak! Hujan adalah temanku, seperti kau juga temanku, Q. Teman tak mungkin menyakiti sahabatnya sendiri. Iya kan, Q.
Aku merindukanmu Q. Hujan yang akan segera berakhir menjelang kemarau ini membuatku sedih. Aku rindu hujan, hujan kita Q.
Dari teman imajiner.
Sukabumi,
Kala musim hujan
Kan berganti
Subscribe to:
Posts (Atom)
